Sufisme yang dianggap Paham Wahdatul Wujud di sebagian kalangan Muslim masih dianggap tabu, atau bahkan menyeramkan bagi siapa saja yang ingin mempelajarinya. Anggapan ini masih bertahan hingga hari ini, terbukti dari banyaknya karya dalam bentuk buku maupun kitab yang masih dapat ditemukan. Karya-karya tersebut umumnya berasal dari kalangan sufi yang memahami Wahdatul Wujud, yang kemudian mereka ekspresikan dalam berbagai bentuk, seperti puisi dan bait-bait syair.
Wahdatul Wujud kerap dianggap sesat, terutama karena tokoh penyebarnya, Al-Hallaj, menuai kontroversi di kalangan Muslim pada zamannya. Dialog dan perdebatan pun muncul mengenai paham ini. Di satu sisi, ada yang menerima pandangan bahwa eksistensi merupakan esensi Tuhan. Namun, para ulama dari kalangan fiqih tidak sependapat dengan pandangan tersebut. Menurut Sami dalam artikelnya yang berjudul Muṣṭafā Ṣabrī on Waḥdat al-Wuǧūd and its Philosophical Origins, Mustafa Sabri memahami Wahdatul Wujud sebagai pengaruh filsafat eksistensialis terhadap para sufi. Mereka yang mempelajarinya akan sampai pada tahap kasf (intuisi intelektual).
Pada abad ke-13, dunia Islam yang semakin terpecah dan penuh konflik berjuang memahami penyebab kelemahannya dan berusaha membalikkan keadaan. Dalam masa yang tidak stabil ini, tasawuf berkembang pesat dan menghasilkan khazanah sastra mistik yang kaya, dalam bentuk risalah, kisah, puisi, dan lagu-lagu sufi. Karya-karya ini kemudian menempati posisi penting dalam berbagai literatur nasional.
Meskipun para mistikus Muslim telah lama memperbarui praktik dan bahasa keagamaan bahkan sebelum istilah tasawuf digunakan secara luas “zaman keemasan” mistisisme Islam umumnya dianggap terjadi dari akhir abad ke-12 hingga abad ke-13. Dari masa inilah muncul tokoh-tokoh penting seperti Muḥyiddīn Ibn al-ʿArabī (1165–1240) dengan spekulasi teosofisnya, Shihāb al-Dīn Yaḥyā al-Suhrawardī (1154–1191) dengan filsafat iluminasi, serta para penyair dan seniman sufi yang menciptakan karya spiritual berupa puisi dan lagu-lagu mistik.
Fenomena munculnya ṭarīqa-ṭarīqa (tarekat-tarekat sufi) di akhir abad ke-12 juga melahirkan bentuk-bentuk puisi dan lagu mistik dalam hampir semua bahasa dunia Islam: Arab klasik, Persia, Turki, Hindi, serta berbagai bahasa daerah di Andalusia dan Afrika Utara. Mayoritas puisi ini, yang ditulis pada abad ke-13, menjadi karya-karya paling dihargai dalam pengabdian para sufisme.
Salah satu tokoh penting dari al-Andalus adalah Abu al-Hasan al-Shushtari (1212–1269), yang dikenal melalui puisi dan nyanyian mistisnya. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Diwan Abu Hasan Al-Shushtari, yang memuat pemahaman dan konteks Islam di Andalusia. Keunikan Shushtari terletak pada pemilihan gaya puisi rakyat yang populer saat itu gaya yang biasanya dianggap kurang serius yang ia transformasikan menjadi syair penuh makna spiritual.
Shushtari menulis dalam bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat Andalusia (bukan Arab klasik). Hal ini membuat puisinya mudah dipahami masyarakat awam, namun menyulitkan penerimaan karyanya di kalangan penutur Arab yang lebih luas. Akibatnya, ia kurang dikenal di dunia Islam secara umum dan karyanya jarang diterjemahkan.
Biografi Abu Hasan Al-Shushtari
Andalusia adalah wilayah di Semenanjung Iberia (sekarang Spanyol dan Portugal) yang dikuasai Islam dari tahun 711 hingga 1492. Selama berabad-abad, wilayah ini mengalami masa kejayaan ilmiah, budaya, dan spiritual—termasuk berkembangnya puisi dan musik. Ini membuktikan bahwa peradaban Islam tidak hanya berpusat di Baghdad.
Namun, sejak abad ke-11 hingga ke-13, al-Andalus mengalami kemunduran politik dan militer. Wilayah Muslim terus menyusut akibat serangan Reconquista oleh kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Keadaan ini menimbulkan ketidakstabilan, ketakutan, dan kehancuran sosial-budaya yang besar.
Dalam buku Sains, Kepustakaan, dan Perpustakaan dalam Sejarah dan Peradaban Islam karya Nurul Hak, disebutkan bahwa para ulama dan intelektual Muslim menunjukkan produktivitas tinggi. Contohnya, Al-Waqidi menulis 400 karya dalam bidang sejarah dan hadis, sedangkan Al-Tabari menghasilkan Tafsir Al-Qur’an. Di masa Sultan Al-Hakam II, peradaban Islam di Andalusia memiliki 70 perpustakaan umum, dan sekolah-sekolah serta madrasah dibuka secara gratis.
BACA JUGA:
Pengalaman Cinta Syekh Muhammad Fuzuli, Sang Sufi Romantis!
Abu al-Hasan al-Shushtari hidup di masa penuh gejolak, ketika kekuasaan Islam di Andalusia mulai runtuh. Dalam kondisi ini, banyak sufi mulai menulis puisi spiritual untuk memberi harapan dan pelarian rohani dari penderitaan dunia. Berikut adalah kutipan syair Al-Shushtari yang dimuat dalam artikel Lourdes Alvarez, The Mystical Language of Daily Life: Vernacular Sufi Poetry and the Songs of Abū Al-Hasan Al-Shushtarī:
“Aku meninggalkan tanah airku agar dapat melihat tanah airmu.
Aku meninggalkan rumahku, tujuanku, kehendak bebasku,
demimu, aku lepaskan segala kepura-puraanku.”
Keberhasilan Al-Shushtari terletak pada kemampuannya merakyatkan puisi sufi. Dengan gaya yang mudah dipahami, ia menyampaikan pesan sufistik seperti cinta Ilahi, kerendahan hati, dan pencarian spiritual ke ruang-ruang publik seperti pasar. Mistisisme tak lagi hanya untuk elite, tapi juga menjadi milik masyarakat umum. Ia menggunakan zajal dan muwashshaha sebagai medium estetik dan spiritual, serta membuka jalan bagi spiritualitas yang inklusif dan membumi.
Tradisi Intelektual dalam Kesusasteraan
Zajal adalah bentuk puisi Arab lisan yang berasal dari tradisi rakyat dan sering dinyanyikan. Puisi ini ditulis dengan bahasa sehari-hari, bukan Arab klasik, sehingga lebih mudah dipahami. Ciri khasnya adalah bait pendek, ritmis, dan melodis—mudah diingat dan dinyanyikan. Dalam karya Shushtari, zajal digunakan untuk menyampaikan pesan spiritual kepada khalayak luas, termasuk pedagang, pengemis, hingga orang biasa di tempat umum.
Sementara itu, muwashshaha adalah puisi berbait-bait (strofik) yang berkembang sejak abad ke-10 di Andalusia. Struktur puisi ini lebih formal dan kompleks dibandingkan zajal. Biasanya ditulis dalam bahasa Arab klasik, tetapi bagian penutupnya (kharja) sering menggunakan bahasa vernakular atau Romance lokal (seperti Mozarab). Dalam karya Shushtari, muwashshaha menjadi media puisi mistik yang terstruktur namun tetap merakyat.
Mempelajari tasawuf atau sufisme tidak seharusnya dianggap sebagai upaya mencapai tingkatan spiritual tertinggi yang eksklusif. Ketika hal itu menjadi ambisi semata, pemahaman sufisme bisa melenceng dan bahkan dianggap sesat atau kafir. Sebaliknya, sufisme perlu dipelajari secara perlahan, melalui literatur dan diskusi terbuka. Dengan demikian, setiap Muslim dapat membuka khazanah intelektualnya tanpa takut disalahpahami.
Bukankah dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, banyak karya sastra sufistik beraliran Wahdatul Wujud seperti karya Hamzah Fansuri yang tetap hidup dan dibaca hingga kini?



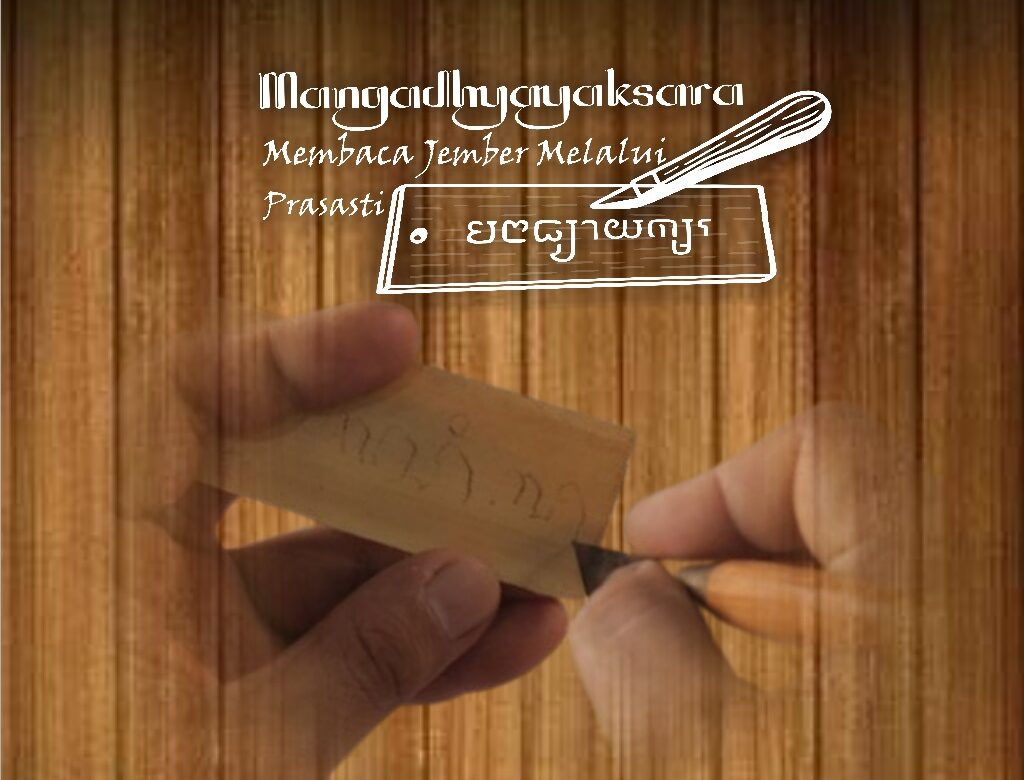

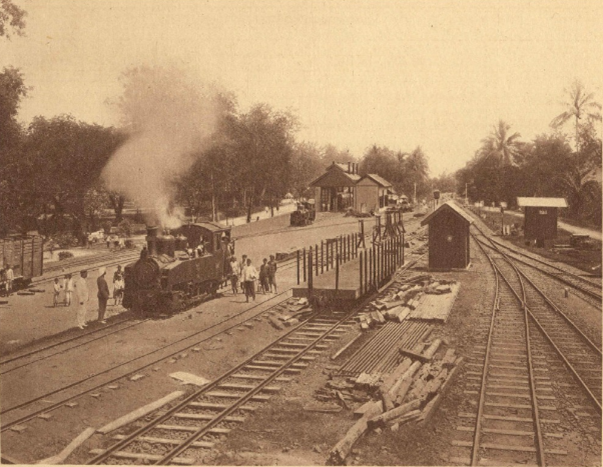


Tinggalkan Balasan