Siapa itu Kafka? Bayangkan Kafka bukan sebagai nama, melainkan sebagai sebuah perasaan. Ia adalah perasaan ketika Anda berdiri di depan loket yang tertutup tanpa penjelasan. Ia adalah kecemasan saat menunggu panggilan telepon yang tak kunjung datang.
Pagi selalu datang dengan pola yang bisa ditebak, suara alarm, kopi hangat, dan rutinitas yang berbaris rapi seperti daftar belanjaan. Tapi, bagaimana jika pada suatu pagi yang tampak biasa, dua orang asing mengetuk pintu dan mengatakan bahwa Anda sedang ditahan? Bukan ditahan secara fisik, melainkan secara hukum, simbolik, dan eksistensial.Tidak ada dakwaan yang jelas, hanya satu kalimat: “Tuan sedang diproses.”
Itulah awal dari (novel Proses), mahakarya Franz Kafka yang tidak menawarkan jawaban, melainkan menyulut pertanyaan tak berujung tentang identitas, kebebasan, dan absurditas hidup modern. Josef K., sang tokoh utama, bukanlah seorang kriminal. Ia adalah pegawai bank biasa yang sibuk, yang merasa hidupnya bisa diatur, hingga dalam semalam seluruh keyakinannya itu runtuh. Yang tersisa hanyalah sebuah tanya getir: “Apa sebenarnya kesalahanku?”
Melalui novel ini, Kafka membongkar sebuah sistem yang dari luar tampak rapi, tetapi sesungguhnya tidak berpihak pada siapa pun. Sebuah prosedur tanpa empati, di mana manusia direduksi menjadi sekadar angka dalam dokumen yang tak pernah tuntas. Kafka tidak menyebut nama sistem itu, tetapi kita semua mengenalnya: birokrasi yang dingin, kekuasaan tanpa tanggung jawab, dan rasa kehilangan arah yang akut dalam masyarakat.
Tulisan ini tidak akan sekadar membaca Kafka dari sisi sastra. Kita akan membawanya ke dalam dialog dengan Carl Rogers, seorang psikolog humanistik, dan salah satu konsep kuncinya. Penerimaan Tanpa Syarat. Bagaimana jika sistem dalam Proses justru memaksa manusia kehilangan kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri? Di sinilah Proses terasa begitu dekat dengan siapa saja yang pernah merasa “tidak punya suara.” Novel ini bukan hanya tentang Josef K, ia adalah tentang aku, kamu, atau siapa pun yang merasa hidupnya dihisap oleh prosedur yang melelahkan. Ketika format lebih diutamakan daripada manusia, yang hilang bukan sekadar keadilan, tetapi juga kemanusiaan itu sendiri.
Resensi ini berusaha membaca ulang Proses sebagai sebuah pengalaman eksistensial melalui lensa konsep penerimaan tanpa syarat Rogers. Kita akan menelusuri: apa yang terjadi ketika manusia kehilangan ruang untuk menjadi dirinya sendiri?
Membaca Sistem Lewat Kafka
Kita tidak sedang membaca fiksi ilmiah. Proses adalah novel yang ditulis Kafka pada 1914–1915, namun baru terbit setelah wafatnya pada 1925. (Sebagai rujukan, edisi bahasa Indonesia terbitan Kakatua dipublikasikan pada tahun 2025). Kafka bahkan tidak sempat menuntaskan naskah ini; ia menitipkannya kepada sahabatnya, Max Brod, dengan pesan untuk dimusnahkan. Namun, Brod justru mewariskannya pada dunia dan bersamaan dengan itu, mewariskan kegelisahan Kafka yang jauh mendahului zamannya.
Dalam Proses, semua hal kehilangan makna. Josef K. hanya disebut dengan inisialnya, tanpa kejelasan identitas. Semua ruang kantor, ruang sidang, kediaman pejabat hadir tanpa alamat atau identitas yang bisa dipercaya. Tidak ada hukum yang jelas atau prosedur yang bisa diikuti. Sistem dalam novel ini apatis dan tak berwajah, mengubah manusia menjadi sekadar bagian dari mekanisme yang tak pernah bisa dipahami.
Kafka tidak sedang menciptakan karikatur yang berlebihan. Ia menulis potret birokrasi yang membeku, berwujud kabut yang tidak bisa disentuh namun sanggup menentukan nasib siapa saja. Sistem dalam Proses bukanlah penjahat yang aktif, melainkan sebuah struktur yang diam dan membusuk, yang menjerat setiap orang dalam absurditas yang terus menyesakkan. Membaca Proses hari ini terasa seperti melihat cermin: ketika urusan administrasi lebih menakutkan daripada rasa bersalah; saat layanan publik menjadi ujian kesabaran; ketika kekaburan dan kerumitan justru dianggap wajar. Kafka seolah memotret masa depan yang perlahan kita jalani, dan di dalamnya kita tidak hanya melihat Josef K., tetapi mungkin juga versi kecil dari diri kita sendiri yang ikut tersesat.
Josef K. dan Keasingan Diri
Orang-orang seperti Josef K. tidak hanya ada dalam cerita Kafka. Mereka nyata: manusia yang menyetor berkas tanpa tahu siapa yang memprosesnya, yang mengurus hak yang tak kunjung diberikan, atau yang sekadar berdiri tanpa daya dalam antrean panjang. Namun, Proses tidak berhenti pada kritik terhadap sistem. Kafka tidak sekadar menunjuk gedung-gedung besar dan struktur kekuasaan tak kasat mata. Ia memperlihatkan bagaimana kekacauan itu berakar hingga ke dalam diri manusia, menyusup ke lapisan kesadaran paling pribadi. Di titik inilah cerita ini bergeser dari kritik sosial menjadi sebuah refleksi eksistensial.
“Begini, Paman,” kata K, “semua itu benar.”
“Benar?” seru pamannya. “Apanya yang benar? Bagaimana ceritanya bisa benar? Kasus macam apa? Bukan kasus pidana, bukan?”
“Kasus pidana,” jawab K.
“Dan kau santai-santai saja di sini padahal namamu tercatut dalam kasus pidana?” seru pamannya dengan suara makin melantang.
“Semakin aku tenang, semakin baik hasilnya,” kata K lelah. “Jangan khawatir.”
“Bagaimana mungkin aku tidak khawatir?” kata pamannya. “Josef, Josef terkasih, pikirkan nasibmu, pikirkan keluargamu, pikirkan nama baik kita. Kau ini kebanggaan keluarga. Sikapmu,” ia menatap K dengan kepala miring, “sikapmu, aku tidak suka; bukan begitu sikap orang tak bersalah yang masih punya kekuatan. Katakan padaku tentang urusan apa kasusmu ini, supaya aku bisa bantu.”
(Proses: 117)
Kutipan di atas menggambarkan secuil dari kesialan Josef K. Ia harus menjelaskan sebuah kasus yang ia sendiri tidak pahami. Ia tidak hanya bingung pada dunia di luarnya, tetapi juga mulai terputus dari dunia di dalam dirinya. Orang-orang berbicara kepadanya, tetapi tidak ada yang mengajaknya berdialog. Ruang-ruang yang ia masuki penuh dengan instruksi, bukan percakapan. Ia hadir sebagai seseorang yang ingin tahu, namun justru semakin kehilangan kemampuan untuk memaknai apa yang terjadi.
Ini bukan soal salah paham, melainkan tentang ketiadaan ruang untuk didengar. Ketika ruang itu lenyap, keasingan bukan lagi soal lingkungan yang tidak ramah, melainkan tentang hilangnya koneksi antara suara batin dengan realitas di luar kepala. Josef K. tetap berbicara, bekerja, dan menjalani hidup. Namun, perlahan, seluruh aktivitas itu kehilangan makna. Prosedur yang menginterogasi jiwanya tidak pernah memberinya satu pun percakapan yang tulus untuk mengenali dirinya sendiri. Hal ini cukup untuk membuat seseorang tercerabut dari apa yang membuatnya merasa hidup.
Kafka tidak berbicara tentang ‘alienasi’ sebagai istilah teoretis; ia menggambarkannya sebagai pengalaman nyata. Ketika seseorang menjalani hidup tetapi tidak merasa menjadi bagian dari hidup itu sendiri, ia memantulkan wajah siapa saja yang pernah kehilangan jati diri bukan karena peristiwa besar, melainkan karena perlahan-lahan terkikis oleh situasi yang rumit. Di titik ini, kita tidak bisa lagi melihat keasingan itu sebagai urusan Kafka semata. Kita harus mulai bertanya: dalam dunia seperti ini, siapa yang bertugas mendengarkan manusia? Siapa yang menjaga agar seseorang tetap merasa dikenali?
Dialog dengan Carl Rogers: Kebutuhan untuk Diterima
Setelah menyusuri samudra keasingan batin Josef K., kita sampai pada satu kesimpulan sederhana: hal yang sering luput dalam percakapan tentang manusia adalah hak dasarnya untuk diakui. Bukan sekadar diizinkan berbicara, tetapi sungguh-sungguh diakui sebagai individu yang memiliki isi kepala, lapisan emosi, dan keinginan untuk dimengerti. Carl Rogers menyebutnya penerimaan tanpa syarat (unconditional positive regard), sebuah sikap yang memungkinkan seseorang merasa aman untuk menampakkan dirinya apa adanya tanpa takut ditolak.
BACA JUGA: Untungnya Kita Punya Danarto: Sastrawan Sufistik yang Nyentrik
Dalam kisah Josef K., kita melihat bahwa yang hilang bukan sekadar keadilan hukum, melainkan sesuatu yang lebih mendasar: kesempatan untuk diterima. Setiap orang yang ditemuinya sibuk menuntut jawaban, memberi arahan, atau sekadar memerintah. Tidak ada yang betul-betul ingin tahu apa yang sedang ia rasakan.
Penerimaan tanpa syarat bukan berarti melegalkan semua tindakan atau membenarkan kesalahan. Ini tentang menyediakan sebuah ruang aman agar seseorang tidak harus memakai topeng untuk bisa berinteraksi. Tanpa ruang itu, manusia perlahan kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Rasa asing tidak lagi hanya datang dari lingkungan, tetapi merembet ke dalam: seseorang mulai ragu pada suaranya sendiri dan mempertanyakan perasaan yang seharusnya menjadi miliknya.
Rogers percaya bahwa hanya dalam relasi yang menerima, seseorang bisa bertumbuh. Ketika tidak ada penerimaan, yang tumbuh justru kecemasan, keraguan, dan rasa bersalah yang tak terjelaskan. Josef K. menjadi simbol manusia yang kehilangan hak paling sederhana ini. Kita melihatnya menghadapi proses demi proses, bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, tetapi yang benar-benar hancur bukanlah fisiknya, melainkan keyakinannya bahwa dirinya layak untuk didengar.
Jika saja di tengah semua kerumitan itu ada satu orang yang mau duduk bersamanya, mendengar tanpa menghakimi, dan bertanya tanpa mengarahkan, barangkali nasib Josef K. akan berbeda. Mungkin bukan hukumnya yang berubah, tetapi cara dia menilai keberadaannya sendiri.
Pada akhirnya, tulisan Rogers bukan sekadar teori psikologi, melainkan sebuah pengingat keras: di luar kemampuan rasional, manusia sangat bergantung pada relasi. Keutuhan diri tidak lahir dari pengetahuan yang hebat, tetapi dari pengalaman diterima apa adanya. Melalui Josef K., kita belajar bahwa tanpa penerimaan, seseorang bisa tetap hidup, tetapi perlahan mati sebagai dirinya sendiri. Dan hal itu, dalam banyak hal, jauh lebih tragis daripada hukuman apa pun.





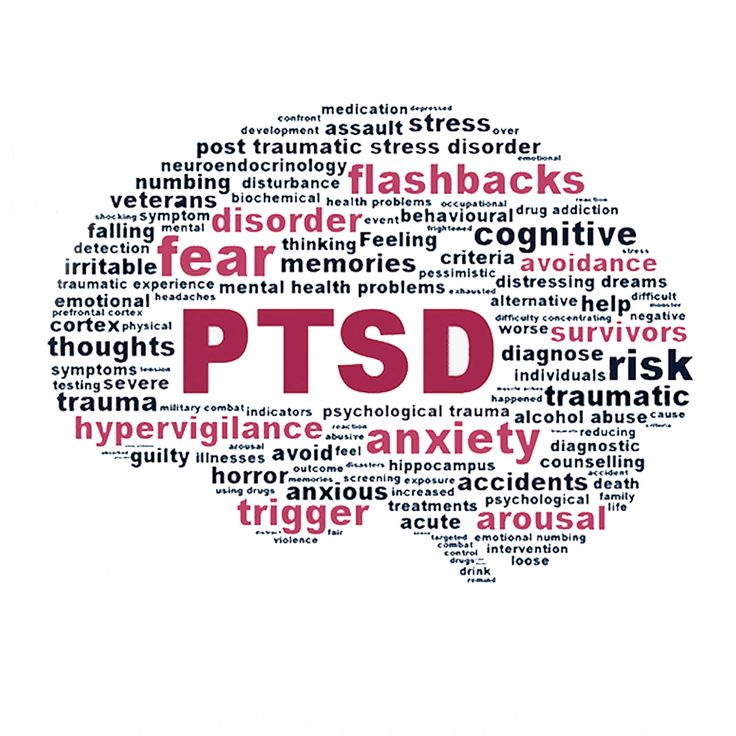


Tinggalkan Balasan