Pesantren merupakan model pendidikan yang memadukan ilmu agama dengan keilmuan formal. Walaupun tidak keseluruhan pesantren mempelajari ilmu formal. Pondok pesantren yang mempelajari ilmu formal biasanya disebut pondok modern atau Khalaf, dan pondok yang hanya mempelajari ilmu agama yang disebut Salaf.
Sebagai lembaga yang mengedepankan nilai-nilai agama, pesantren seolah menjadi kiblat bagi masyarakat, walaupun beberapa tahun terakhir berita mengenai pesantren seolah menjadi engagement konten terbaik untuk meningkatkan trafik.
Namun kali ini, alih-alih membahas permasalahan yang sama dalam dunia pesantren, bagaimana jika kita bahas gaji? Hal ini penting bukan karena naiknya gaji DPR tentunya, melainkan banyaknya korban alumni yang kembali atas panggilan batin untuk mengajar, lalu terjebak dalam perangkap barokah.
Sebut saja Hasbi (bukan nama sebenarnya) adalah alumnus Magister Sejarah Peradaban Islam dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam beberapa tahun terakhir, ia memfokuskan kajiannya pada bidang filologi.
Sebagai seorang filolog, Hasbi aktif menginisiasi berbagai acara edukasi, seperti “Kajian Naskah Nusantara” yang telah diselenggarakan di berbagai kota. Ia juga pernah berkontribusi dalam proyek DREAMSEA, sebuah program yang berfokus pada digitalisasi dan pelestarian manuskrip yang terancam punah di Asia Tenggara.
Selama menjelajah pasca kehidupan magister, Hasbi ingin kembali ke salah satu pesantren ternama yang berada di daerah Situbondo yakni melamar sebagai dosen Sejarah. Sesampai di tempat, Hasbi memperlihatkan portofolio dan CV yang sudah ia tekuni.
“Portofolio Anda di luar ekspektasi kami, Mas. Tapi, kami di sini mengedepankan pengabdian dan bisa memberi gaji 500 ribu perbulan,” ujar HRD, Senin (14/07/25).
Sontak Hasbi tercengang dan tidak bisa berkata banyak. Dengan gaji tersebut, rasanya hanya pas untuk bayar kos, mengingat Hasbi berdomisili Jember. Orang tua Hasbi juga tidak menanggapi banyak tentunya dengan kabar tersebut. “Gaji 500 ribu buat bayar kos aja udah nggak cukup,” ujar Hasbi.
Kapitalis Dalam Bentuk Paling Suci
Setelah kalimat dari HRD itu menggantung di udara, ruangan terasa senyap. Otak Hasbi yang terlatih mengurai aksara kuno dan melacak jejak peradaban kini dipaksa melakukan kalkulasi yang jauh lebih brutal, mengonversi “pengabdian” dan “barokah” ke dalam kurs Rupiah yang berlaku di warung kopi dan konter pulsa. Hasilnya nihil. Ia membayangkan skenario paling absurd, mencoba membayar tagihan Indihome dengan segenggam pahala atau menawarkan doa kepada ibu kos sebagai pengganti uang sewa. Tentu saja, ia akan diusir sebelum doanya selesai diaminkan.
Di hadapannya, sang HRD tersenyum dengan penuh kearifan. Senyum yang seolah berkata, “Anak muda, kamu belum paham esensi kehidupan. Dunia ini fana, yang abadi adalah ganjaran di akhirat.” Ini adalah senyum standar operasional dalam ekosistem kerja yang menjadikan loyalitas sebagai mata uang, dan kesejahteraan sebagai cobaan iman.
BACA JUGA: Panduan Pahit yang Tak Diajarkan di Materi Ospek Maba
Hasbi tiba-tiba merasa seperti sedang membaca sebuah naskah kuno yang ironis. Di satu sisi, ada narasi besar tentang mencerdaskan kehidupan bangsa dan merawat tradisi keilmuan. Di sisi lain, ada pasal-pasal tak tertulis yang mengharuskan para pelakunya hidup dalam kondisi semi-fakir, seolah kemiskinan adalah stempel keikhlasan yang paling kapitalis.
Dari balik jendela kantor yang ber-AC itu, Hasbi bisa melihat bangunan pesantren yang berdiri megah. Ia juga menangkap siluet mobil milik Kiai pimpinan pondok yang mengkilap sebuah seri terbaru yang jelas tidak dibeli menggunakan diskon akhirat. Seketika, sebuah hipotesis liar terbentuk di benak Hasbi, mungkin “barokah” ini adalah sebuah sistem distribusi. Ia mengalir deras dari keringat para pengabdi di level bawah, lalu menguap ke atas, dan akhirnya mengkristal menjadi aset-aset duniawi yang sangat konkret di level puncak.
Panggilan batin untuk mengabdi itu nyata, Hasbi mengakuinya. Namun, panggilan dari perut yang minta diisi setiap hari dan tagihan dari provider internet yang ia gunakan untuk riset juga sama nyatanya. Ia, seorang filolog yang berjuang menyelamatkan masa lalu dari kepunahan, kini dihadapkan pada pilihan untuk membiarkan masa depannya sendiri terancam punah serupa distopis.
Dengan tarikan napas panjang, Hasbi mengumpulkan kembali kesadarannya. Ia menatap CV-nya yang berisi pengalaman proyek internasional dan keahlian langka, lalu membandingkannya dengan nominal 500 ribu. Rasanya seperti menukar sebuah artefak berharga dengan sebungkus kerupuk.
Pada akhirnya, Hasbi sadar bahwa pengabdian terbesar adalah memastikan dirinya tetap hidup dan waras. Sebab, bagaimana ia bisa menularkan ilmu dan melestarikan peradaban jika otaknya terus-menerus disibukkan oleh cara bertahan hidup dari tanggal 15 ke tanggal 30? Dengan sopan, ia pamit undur diri, meninggalkan “investasi akhirat” itu di atas meja untuk para pencari barokah sejati lainnya.

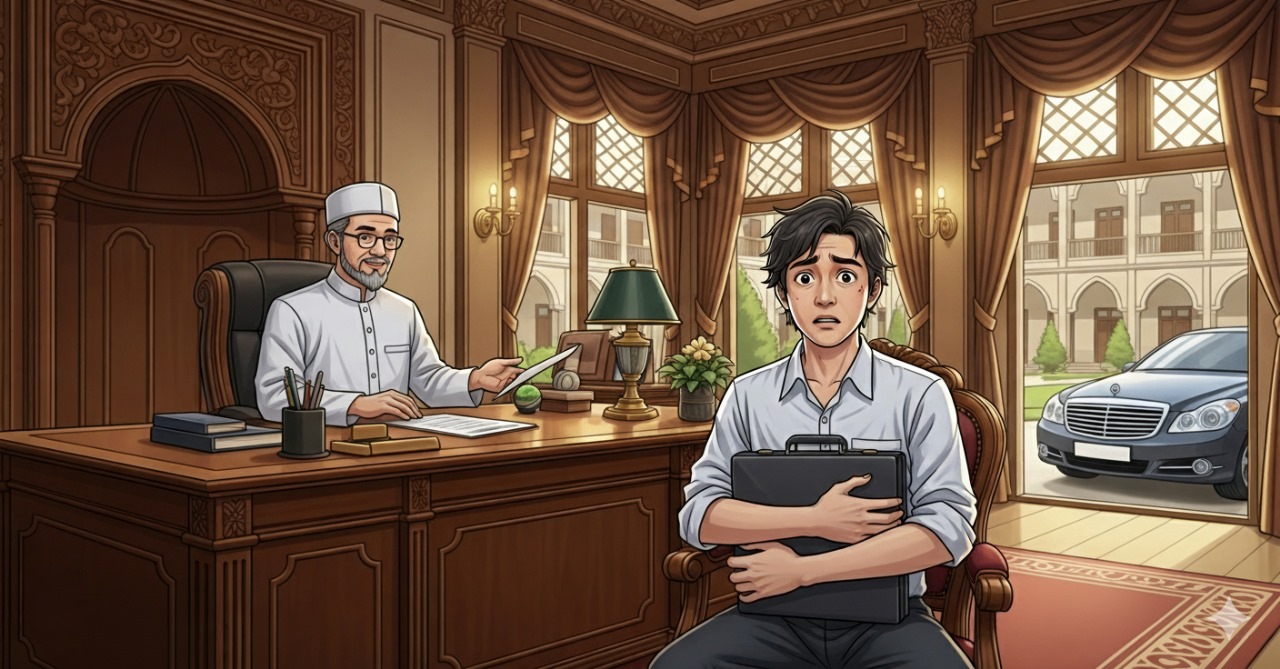



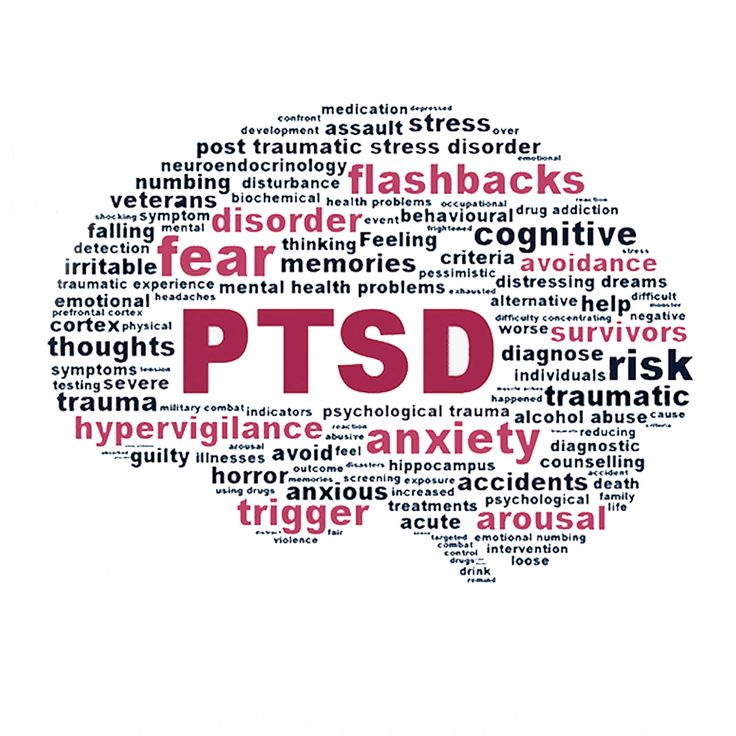


Tinggalkan Balasan