Apakah Anda punya kebiasaan membeli buku yang tak pernah sempat Anda baca? Ternyata Anda tidak sendirian. Bahkan, orang Jepang punya istilah yang indah sekaligus penuh ironi: tsundoku. Kata ini merujuk pada kebiasaan membeli buku, menyimpannya, menumpuknya di rak atau meja, tetapi tidak pernah benar-benar membacanya.
Bagi sebagian orang, tsundoku tampak seperti kebiasaan buruk, semacam pengkhianatan terhadap janji pada diri sendiri ketika kita membeli buku dengan niat yang tulus: “aku akan membacamu suatu hari nanti.” Namun, bagi sebagian yang lain, tsundoku adalah seni dalam dirinya sendiri, sebuah cara manusia modern mengelola hasrat, keingintahuan, sekaligus kelemahannya.
Bayangkan seseorang berjalan masuk ke sebuah toko buku. Di dalamnya, aroma kertas baru menyeruak, halaman-halaman segar memanggil dari rak-rak tinggi yang penuh sesak. Setiap sampul buku seperti memiliki magnet tersendiri: ada novel yang katanya memenangkan penghargaan internasional, ada buku filsafat yang menjanjikan jawaban atas kegelisahan, ada karya sastra klasik yang seakan wajib dimiliki oleh siapa pun yang menyebut dirinya pembaca.
Orang itu, dengan langkah penuh semangat, memilih satu, dua, lalu tiga buku. Di kasir, ia menatap kantong kertas berisi lembaran masa depan: janji-janji untuk menjadi pribadi yang lebih berpengetahuan, lebih bijak, lebih berbudaya. Tetapi beberapa minggu kemudian, buku-buku itu masih tergeletak di meja, plastik pembungkusnya belum juga disobek.
Di sinilah tsundoku memperlihatkan dirinya. Ia adalah tumpukan buku yang menjadi semacam monumen bagi niat yang tertunda, keinginan yang terperangkap dalam rutinitas, atau sekadar obsesi koleksi. Tsundoku bukanlah kemalasan murni, melainkan kombinasi dari rasa lapar akan pengetahuan dan keterbatasan waktu untuk benar-benar menikmatinya. Dalam bahasa sederhana, tsundoku adalah cermin kehidupan manusia modern: penuh dengan keinginan, namun selalu kekurangan waktu.
Uniknya, tsundoku tidak hanya berlaku pada mereka yang memang gemar membaca. Ada orang yang membeli buku hanya untuk sekadar merasa dekat dengan dunia literasi. Buku-buku itu mungkin tidak pernah dibaca, tetapi kehadirannya menenangkan. Rak penuh buku bisa menjadi simbol status, tanda kecerdasan, bahkan bentuk estetika. Sebagian orang menata buku-buku tak terbaca itu di ruang tamu, seperti menata lukisan atau vas bunga, agar tamu yang datang bisa melihat: “Aku punya dunia di sini.” Ada kebanggaan terselubung dalam menampilkan deretan buku, meskipun sebagian besar hanya sekadar hiasan.
Tsundoku tidak selalu harus dianggap sebagai kelemahan atau kesia-siaan. Justru di balik kebiasaan ini, ada filosofi yang menarik. Membeli buku berarti mengakui bahwa kita punya rasa ingin tahu, ada hasrat untuk berkembang. Meskipun buku itu belum terbaca, tindakan memilikinya sudah merupakan bentuk keterhubungan dengan pengetahuan. Seperti seseorang yang membeli benih pohon tetapi belum sempat menanamnya, buku adalah potensi yang selalu ada. Setiap kali kita menatap tumpukan buku itu, kita seperti diingatkan pada kemungkinan: “Aku bisa membacanya suatu hari nanti.”
Filsuf Nassim Nicholas Taleb pernah memperkenalkan istilah antibibliotek, yang kurang lebih sejalan dengan tsundoku. Ia menyebut bahwa buku-buku yang tidak terbaca justru lebih berharga daripada buku yang sudah kita baca, karena tumpukan itu mewakili ruang pengetahuan yang belum kita kuasai, wilayah misterius yang selalu memanggil untuk dijelajahi.
Koleksi buku yang belum terbaca adalah simbol kerendahan hati, pengakuan bahwa kita masih kecil di hadapan luasnya samudra ilmu. Jika kita sudah membaca semua buku di rak, mungkin kita akan jatuh pada kesombongan, merasa sudah tahu segalanya. Tetapi justru dengan melihat rak penuh buku yang belum sempat disentuh, kita diajak untuk menyadari betapa banyaknya yang belum kita pahami.
Dalam konteks ini, tsundoku bukan hanya soal menunda membaca, melainkan juga soal menyusun diri. Buku-buku yang kita beli merepresentasikan keinginan terdalam: ada orang yang mengoleksi buku filsafat, mungkin karena ia haus akan makna hidup; ada yang menumpuk buku traveling, mungkin karena ia merindukan kebebasan menjelajahi dunia; ada yang membeli banyak novel romansa, karena ia ingin merasakan cinta yang mungkin tak ia dapatkan di kehidupan nyata. Dengan kata lain, rak buku yang penuh dengan tumpukan bacaan yang belum tersentuh bisa dibaca sebagai cermin psikologis dari pemiliknya.
Meski begitu, tsundoku tetap mengandung sisi getir. Ada rasa bersalah yang perlahan menumpuk seiring bertambahnya buku. Setiap kali kita melirik rak, ada suara kecil yang berbisik: “Kapan kau akan membacaku?” Sebagian orang menyamakan hal ini dengan kebiasaan menunda dalam bentuk lain: menunda diet, menunda olahraga, menunda pekerjaan. Buku-buku itu menjadi saksi diam atas kegagalan kita melawan rasa malas. Dan ironisnya, semakin banyak kita menumpuk buku, semakin berat rasa bersalah itu.
Apakah salah bila buku hanya dikoleksi, bukan dibaca? Mungkin pertanyaan itu tak butuh jawaban mutlak. Ada orang yang menemukan kebahagiaan hanya dengan memiliki, memegang, dan mencium bau kertas baru. Buku bisa dilihat sebagai benda estetik, seperti seni rupa. Tidak semua orang membeli lukisan untuk memahami maknanya, sebagian hanya karena lukisan itu indah. Begitu pula dengan buku: ada yang membelinya untuk dibaca, ada juga yang membelinya karena ia suka berada di tengah-tengah buku.
Dalam kehidupan modern yang serba cepat, tsundoku juga bisa dimaknai sebagai bentuk resistensi. Kita tahu kita tak akan punya cukup waktu untuk membaca semua, tetapi kita tetap membeli buku sebagai tanda perlawanan terhadap arus digital yang instan. Di tengah banjir informasi singkat dari media sosial, berita kilat, dan video berdurasi detik, buku hadir sebagai simbol ketekunan. Mungkin kita tidak langsung membacanya, tapi kita sudah memberi ruang pada sesuatu yang berbeda: sesuatu yang memerlukan kesabaran, fokus, dan perenungan.
BACA JUGA: Review Book: Teori dan Metode Filologi Dalam Sudut Pandang Buku karya Prof Oman Faturrohman
Bagi sebagian orang, tsundoku adalah ritual kecil yang menenangkan. Proses memilih buku, membuka plastiknya, menatap sampulnya, bahkan menatanya di rak sudah memberi kepuasan tersendiri. Ada semacam perasaan bahwa hidup ini masih punya arah, bahwa di tengah rutinitas melelahkan, kita masih menyisakan ruang untuk imajinasi dan pengetahuan. Buku-buku itu adalah pengingat bahwa hidup tidak hanya soal bekerja, makan, dan tidur, tetapi juga soal mencari makna.
Mungkin, tsundoku seharusnya tidak dilihat sebagai dosa, melainkan sebagai cara manusia menjaga kemungkinan. Setiap buku yang belum dibaca menyimpan janji. Ia bisa menjadi teman di masa pensiun, penolong di masa sulit, atau sekadar penghibur di malam sepi. Kita tidak pernah tahu kapan satu buku akan benar-benar berguna. Mungkin selama bertahun-tahun ia terdiam di rak, lalu suatu hari, entah karena tak sengaja atau dorongan tertentu, kita membukanya dan menemukan kalimat yang mampu mengubah hidup.
Dalam dunia yang semakin pragmatis, di mana segala hal diukur dari hasil, tsundoku hadir sebagai pengingat bahwa tidak semua yang kita lakukan harus segera menghasilkan sesuatu. Ada nilai dalam menunggu, dalam menunda, bahkan dalam menumpuk. Rak penuh buku tak terbaca bisa dilihat sebagai tumpukan potensi, reservoir ide yang suatu saat bisa meledak menjadi inspirasi. Dan meski kita mungkin tidak akan pernah membaca semuanya, buku-buku itu tetap menyusun kita secara diam-diam: membentuk identitas, membentuk citra diri, bahkan membentuk cara orang lain memandang kita.
Tsundoku adalah paradoks yang indah. Ia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang penuh hasrat sekaligus penuh keterbatasan. Kita ingin tahu banyak hal, tetapi waktu tak pernah cukup. Kita ingin menjadi lebih bijak, tetapi sering terjebak dalam kesibukan. Namun, justru dalam paradoks itulah letak keindahannya. Tsundoku mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu tuntas. Ada hal-hal yang bisa dibiarkan terbuka, ada pertanyaan yang tidak perlu segera dijawab, ada buku yang cukup kita biarkan menunggu di rak, seperti sahabat yang setia.
Seni tsundoku bukan tentang membaca buku, melainkan tentang membaca diri sendiri. Membaca apa yang kita rindukan, apa yang kita takutkan, dan apa yang diam-diam kita dambakan. Setiap buku yang kita beli dan biarkan menumpuk adalah fragmen dari jiwa kita. Dan meski halaman-halamannya belum terbuka, ia sudah berbicara banyak tentang siapa kita.





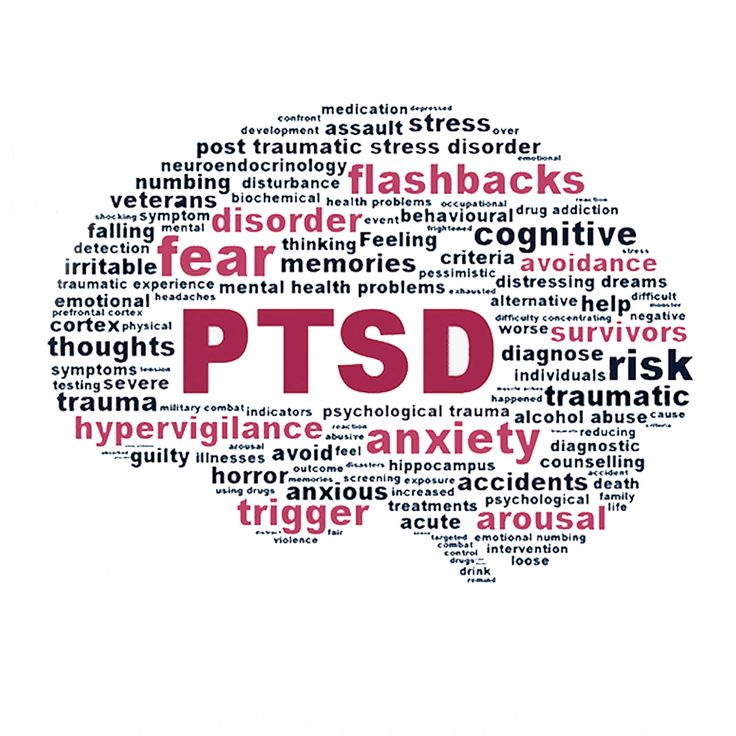


Tinggalkan Balasan