Akhir-akhir ini, dunia pers sedang dihebohkan dengan teror kiriman kepala babi dan disusul dengan bangkai tikus yang terjadi di kantor Tempo. Paket misterius ini ditujukan kepada salah seorang wartawan majalah Tempo, meskipun kebebasan pers di Indonesia sudah dijamin tetapi nyatanya membicarakan teror terhadap kerja jurnalisme merupakan hal yang menarik.
Karena selama ini banyak pelaku (lebih tepatnya oknum) yang menodai kebebasan pers. Hal-hal yang dilakukan banyak pihak yang membuat semakin beratnya menegakkan etika jurnalisme dengan benar.
Pihak yang berseberangan dengan kebenaran realita selalu memojokkan jurnalisme sebagai musuh yang harus dijegal bahkan dibumihanguskan. Padahal, idealnya pers beserta seluruh jajaran jurnalis harus diberdayakan seiring dengan cita-cita bersama sejak masa reformasi.
Ketika reformasi digulirkan, harapan terbesar terhadap pers diharapkan menjadi penegak semangat kebenaran dalam penataan sendi kehidupan. Itu menjadi harapan, bukan sekedar utopia semata. Namun, persoalannya kemudian semua pihak harus memberikan apresiasi yang besar terhadap pekerja pers (jurnalis). Sehingga tanpa itu semua, pers nasional tidak akan bermakna besar bagi kehidupan.
Bentuk-bentuk penodaan terhadap jurnalis yang bisa mencederai jumalisme, telah banyak dilakukan. Baik oleh instansi pemerintah atau bahkan individu sipil yang memiliki tujuan tertentu dalam melakukan itu semua. Titik kulminasi dari hal itu adalah pemandulan terhadap pers, padahal pers nasional harus tetap berdiri dalam membangun masyarakat.
Tragedi 23 Januari di Kantor Harian Waspada
Gemparnya dunia pers baru-baru ini yang sedang di teror, di masa lalu juga pernah terjadi hal serupa yaitu di kantor Harian Waspada Medan. Pada tahun 2002, kekerasan dan kebrutalan terjadi di kantor Harian Waspada yang dilakukan oknum polisi dengan memaksa masuk ke kantor itu serta memberi “hadiah” kepada salah seorang wartawannya dan petugas keamanan.
Tentu hal ini merupakan teror dan bentuk pencederaan yang dilakukan aparat negara. Semestinya tragedi itu tidak terjadi manakala seluruh anggota polisi mengetahui etika jurnalisme dan oknum itu tidak akan melalukan kegiatan yang tidak sepantasnya itu di kantor Harian Waspada.
Dari segi manapun, tindakan yang dilakukan oknum itu tidak dapat dibenarkan. Karena hal itu merupakan bentuk brutalisme yang dilakukan pelindung masyarakat, sebagaimana predikat yang selama ini melekat pada polisi. Selanjutnya pihak Harian Waspada menuntut untuk semestinya permintaan maaf yang dilakukan oleh Polri dan diiringi dengan pengusutan secara tuntas.
Tetapi pada kenyataanya, setelah tragedi itu terjadi tuntutan yang diharapkan itu tidak kunjung dilakukan. Dan pantas saja jika selama ini masyarakat merasakan jika ada anggota TNI/Polri yang melakukan tindakan kesalahan, selalu diselesaikan di lingkungan intern saja. Itu akan memancing tanda tanya masyarakat luas, apakah memang kasus itu diselesaikan dengan baik atau malah dibiarkan.
BACA JUGA:
RUU TNI: Urgensi Atau Hanya Sebagai Alat Memperkuat Kekuasaan
Membayangkan Orde Baru (Reborn)
Hal ini merupakan bentuk pengambilan tindakan yang tidak transparan, sehingga efeknya masyarakat tidak bisa memantau kebenaran ucapan pejabat di tubuh TNI/Polri yang mengatakan bahwa anak buahnya yang melakukan pelanggaran itu sudah dikenai tindakan.
Masyarakat melihat apa yang dilakukan masih sebatas retorika dan upaya pelindungan yang membabi buta terhadap anak buahnya. Tentu saja hal ini dirasakan sebagai sebuah ketidakadilan. Polri sebagai institusi yang seharusnya dengan segera menuntaskan kasus itu.
Justru pada tragedi itu, pihak Polri menganggap bahwa telah terjadi penggiringan opini. Sebab, sebagaimana yang diungkapkan salah seorang pejabat Polri di jajaran Kepolisian Resor Kota Besar Medan saat itu bahwa ada orang yang menyamar sebagai anggota Polisi. Ucapan itu dikeluarkan setelah beberapa hari pengusutan tidak ditemukan anggota Polisi yang bertugas waktu itu mengakui masuk ke kantor Harian Waspada. Hal ini menjadi mustahil ada pihak lain yang menyamar sebagai anggota Polisi yang memaksa masuk ke kantor Harian Waspada.
“Mana ada maling yang mau mengaku!” peribahasa ini kemudian menjadi slogan relevan. Sebab, oknum polisi itu mengetahui bahwa kalau dirinya mengakui, maka akan mendapatkan tindakan disiplin (hukuman). Di sinilah sebenarnya tuntutan kemampuan Polri dalam mengusut kasus.
Jika benar ada orang yang menyamar sebagai anggota Polisi, maka tampak sekali secara nyata bahwa Polri memiliki kelemahan yang sangat besar. Karena bisa dengan mudah orang lain menyamar sebagai anggota Polisi. Sehingga ucapan pejabat ini menurunkan citra Polri sendiri, padahal semestinya Polisi tetap menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Apalagi mereka sebagai kelompok yang homogen yang bisa dikontrol dengan variabel tertentu.
Karena kasus yang berkepanjangan dan belum juga menemui titik terangnya, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan tidakan guna menyelesaikan kasus ini, sebagaimana janji yang diucapkan Kepala Dinas Hukum Kombespol H. Pakpahan di depan anggota DPRD Sumatera Utara pada 4 Februari 2002.
Hal ini sangat dinantikan masyarakat, terlebih insan pers agar tidak terulang pada yang lainnya. Tragedi 23 Januari itu tidak akan terjadi jika anggota Polisi itu sebagai institusi profesional menghargai hak masyarakat. Wajar, jika selama ini ada masyarakat bertanya-tanya dan bahkan tidak percaya dengan kinerja aparatur kepolisian.
Lantas apa yang dapat diteladani dengan mengingat tragedi 23 Januari Harian Waspada itu? Tentu tidak lain adalah melihat bahwa penanganan terhadap sebuah kasus yang menimpa pada dunia pers cenderung lambat, sehingga berdampak dengan munculnya wacana bahwa pers akan kembali kemasa suramnya yakni pada masa Orde Baru, dimana pembungkaman terhadap pers sangat masif.





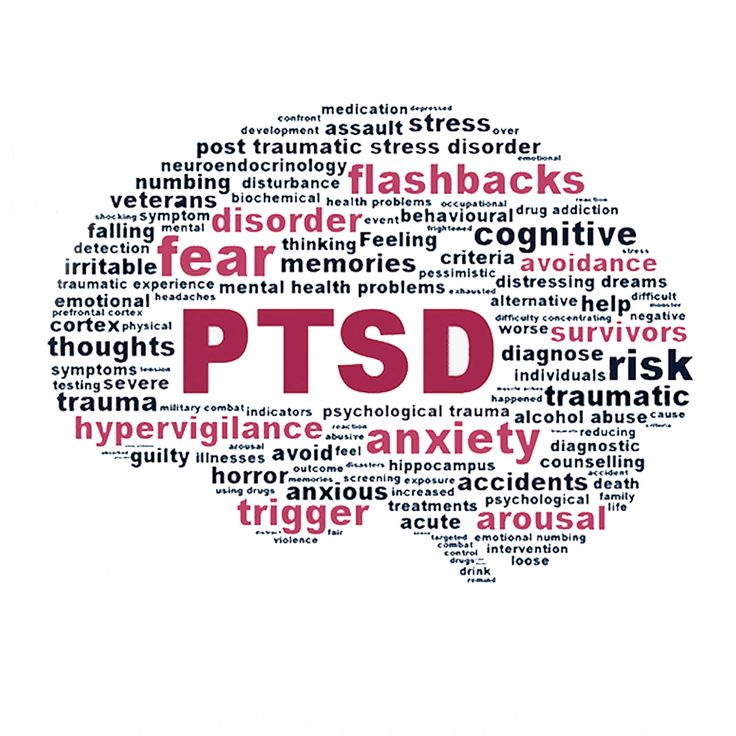


Tinggalkan Balasan