Di tengah keriuhan politik yang tak pernah surut, narasi-narasi yang beredar di ruang publik sering kali terasa lebih familier dengan panggung sinema ketimbang mimbar parlemen. Fenomena ini, yang oleh banyak pengamat disebut sebagai populisme, telah menjadi inti dari cara kerja politik di Indonesia hari ini. Populisme modern adalah seni mengelola persepsi, di mana kekuasaan tidak lagi diukur dari kebijakan yang substantif, melainkan dari seberapa kuat sebuah citra dapat memikat hati rakyat.
Dari Radio ke Media Sosial: Lahirnya Politik Panggung
Sejak awal abad ke-20, para pemimpin populis telah memahami satu hal, kekuasaan bukan hanya soal kebijakan, tapi juga soal panggung. Ini bukanlah fenomena baru. Jauh sebelum era digital, politisi sudah memanfaatkan media untuk membangun citra yang memikat. Di Amerika Serikat tahun 1930-an, Presiden Franklin D. Roosevelt menggunakan radio melalui program “Fireside Chats”. Seperti dijelaskan oleh J. Michael Hogan dalam bukunya Voice of Democracy, suara Roosevelt yang tenang menciptakan kedekatan emosional, seolah ia hadir di ruang keluarga pendengarnya.
Lompatan besar terjadi saat televisi lahir. Debat John F. Kennedy vs. Richard Nixon pada tahun 1960 menjadi titik balik. Sejarawan David Greenberg, dalam bukunya Republic of Spin, mencatat bahwa yang menang bukanlah argumen terbaik, melainkan penampilan yang paling “telegenik.” Kennedy yang segar dan fotogenik mengalahkan Nixon yang pucat dan berkeringat. Sejak itu, politik tidak bisa lagi lepas dari kekuatan visual.
Taktik ini kemudian diadaptasi oleh pemimpin populis di berbagai negara, dari Juan Perón di Argentina yang menggunakan film dokumenter untuk narasi pro-rakyat, hingga Silvio Berlusconi di Italia yang membangun kerajaan media untuk memoles citranya. Mereka semua memahami bahwa politik adalah pertunjukan.
Ketika “Blusukan” Menjadi Strategi
Dengan hadirnya media sosial, panggung politik meluas hingga ke genggaman miliaran orang. Di Indonesia, fenomena ini menemukan bentuk paling khasnya pada sosok Presiden Joko Widodo. Sejak menjabat sebagai Walikota Solo, ia mempopulerkan “blusukan” yang direkam, dibingkai, dan diunggah ke YouTube serta media sosial. Akademisi Ross Tapsell, dalam bukunya Media Power in Indonesia, menyebut strategi ini sebagai political branding berbasis visual. Blusukan tidak lagi sekadar kunjungan, melainkan sebuah pertunjukan yang konsisten menegaskan citra pemimpin yang merakyat.
Gaya ini menular ke banyak politisi daerah. Ridwan Kamil menggunakan media sosial dengan bahasa gaul untuk program seperti “Saber Hoax,” sementara Dedi Mulyadi menciptakan semacam reality show politik di YouTube, menampilkan dirinya yang langsung membantu warga atau menegur mereka di depan kamera. Tujuan mereka sama: membangun citra yang dekat dan berbeda dari birokrat kaku, menjadikan aksi spontan, dramatis, dan emosional sebagai modal utama pencitraan.
Gimmick sebagai Kebijakan
Masalah muncul ketika gimmick tidak lagi hanya menjadi alat komunikasi, tetapi berubah menjadi substansi politik itu sendiri. Para pemimpin populis cenderung mengutamakan “governing by headline,” atau memerintah untuk menciptakan berita utama. Alih-alih merumuskan kebijakan yang rumit, mereka fokus pada proyek-proyek yang mudah divisualisasikan, seperti jalan tol, kartu bantuan sosial, atau pembagian seragam gratis yang fotogenik.
Fenomena ini, seperti yang disampaikan Murray Edelman dalam bukunya Politics as Performance, menunjukkan bahwa publik sering kali tidak bisa membedakan antara kebijakan nyata dengan kebijakan simbolis. Di Filipina, kebijakan “perang melawan narkoba” Rodrigo Duterte, menurut laporan New York Times, lebih merupakan aksi teatrikal untuk menampilkan citra pemimpin yang kuat daripada program komprehensif yang mengatasi akar masalah narkoba.
BACA JUGA: Perlawanan Sunyi, Petani di Ujung Timur Jawa 1890-1930
Di Indonesia, hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan publik. Sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak luput dari logika panggung. Pembangunan rumah sakit atau peresmian jalan sering kali dikemas layaknya acara hiburan dengan tujuan mendapatkan sorotan media. Namun, isu-isu mendasar seperti kekurangan tenaga medis atau pemeliharaan yang tidak berkelanjutan, jarang mendapat panggung yang sama.
Demokrasi dalam Ujian: Tuntutan 17+8
Taktik-taktik ini, yang mengutamakan citra di atas segalanya, pada akhirnya membentuk sebuah lingkaran setan. Rakyat terbiasa disuguhi pertunjukan, sementara para pemimpin sibuk memproduksi konten dan Flexing. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, publik mulai merasakan kejenuhan. Di tengah keriuhan politik yang berfokus pada gimik, muncul gelombang suara yang menuntut kembalinya substansi.
Hal ini terlihat nyata dalam Tuntutan 17+8 yang digemakan oleh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil. Tuntutan ini bukan sekadar protes; ia adalah representasi dari kegelisahan publik terhadap praktik politik yang semakin menjauh dari esensinya. Tuntutan ini secara spesifik meminta pertanggungjawaban atas berbagai isu fundamental, mulai dari isu ekonomi, ketidakpastian hukum, hingga pelemahan lembaga-lembaga demokrasi. Ia mencerminkan kerinduan akan politik yang jujur, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat secara substantif, bukan hanya simbolis.
Tuntutan 17+8 adalah bukti bahwa politik panggung telah mencapai batasnya. Ia adalah seruan untuk menghentikan pertunjukan dan kembali pada esensi kepemimpinan. Masa depan demokrasi Indonesia akan ditentukan oleh apakah para pemimpin akan mendengarkan tuntutan ini atau tetap bertahan dalam lingkaran populisme visual yang pada akhirnya, akan membuat politik kita tidak hanya kosong, tetapi juga kehilangan arahnya.



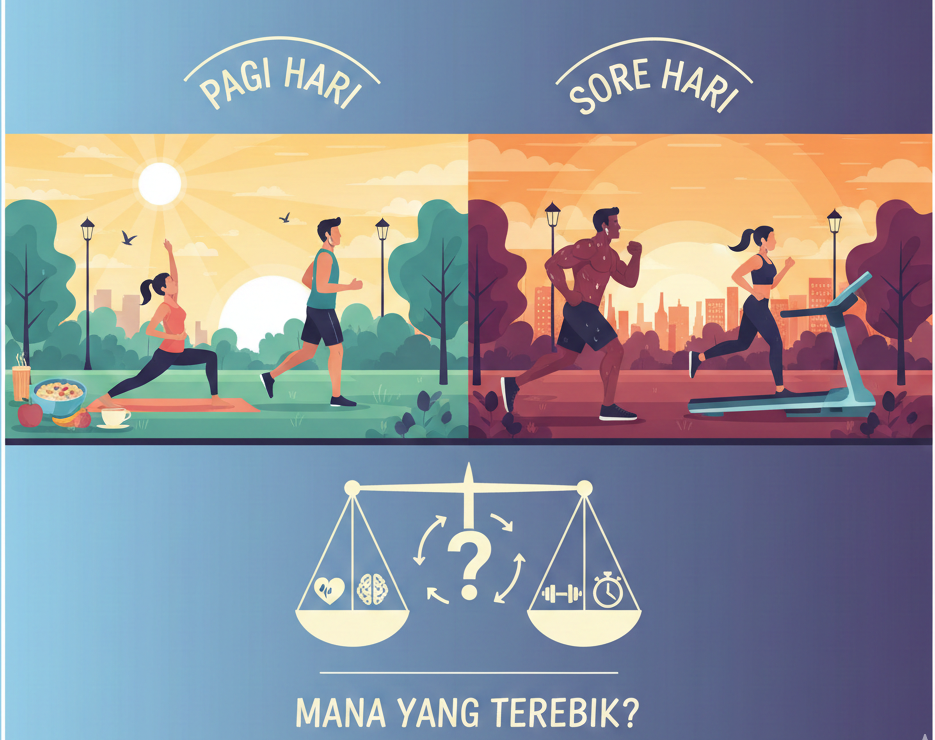

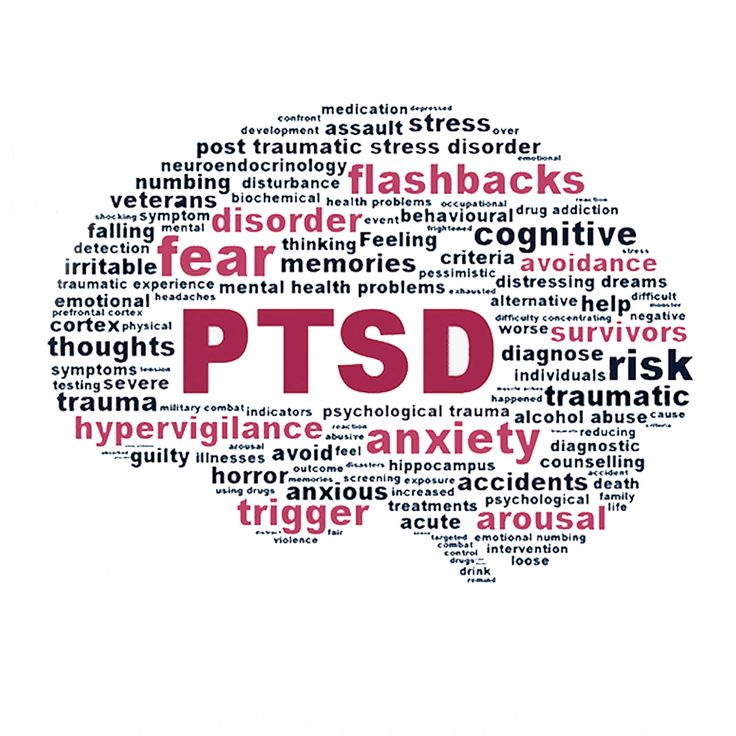

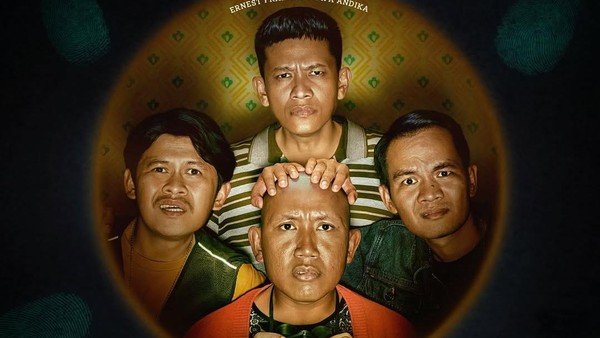
Tinggalkan Balasan