Dunia berputar lebih cepat dari putaran otak di sebuah kedai kopi. Teknologi melesat, inovasi bermunculan bagai jamur di musim hujan, dan tuntutan akan kemampuan praktis yang bisa diukur dengan angka dan profit semakin mendominasi. Di tengah hiruk-pikuk ini, sebuah pertanyaan fundamental kembali menyeruak, bukan dari ruang kelas berdebu, melainkan dari panggung podcast modern, di manakah posisi filsafat? Apakah ilmu kebijaksanaan yang telah ribuan tahun menemani peradaban manusia ini masih relevan, ataukah ia hanya menjadi relik kuno yang pas untuk pajangan?
Perdebatan ini mencuat tajam dalam podcast “Pendidikan dan Cacat Pikir Zero-Sum Game Bitcoin,” di mana Ferry Irwandi berdialog dengan Timothy Ronald. Awalnya pembicaraan mereka sama seperti pembicaraan pada podcats featuring sebelum-sebelumnya. Namun semenjak statement Ferry Irwandi dengan gaya lugasnya yang melontarkan kritik cukup tajam yaitu jurusan filsafat, menurutnya, harus dihapus. Alasannya sungguh pragmatis, tidak cocok lagi dengan “skill dan positioning” yang dibutuhkan dunia serba fast-paced ini. Baginya, filsafat bak hantu masa lalu, lahir di era ketika otak manusia masih mengandalkan hipotesis dan asumsi karena smartphone belum ditemukan.
Timothy Ronald, Ia tidak serta merta menampik statement Ferry. Sebaliknya, Timothy juga berpendapat apakah filsafat, dengan segala kemegahannya, telah berfungsi pada tempatnya? Ataukah ia justru terjebak dalam menara gading teori, sibuk dengan istilah Yunani kuno, tapi lupa bagaimana berdialog dengan tagihan listrik bulanan? Mungkin begitu jika diberi sentuhan humor satire.
Relevansi Filsafat: Sebuah Kompas, Bukan Kamus Kosong
Inilah inti dari perdebatan yang seringkali keliru dipandang sebagai “perang” barbar antara ilmu humaniora dan eksakta. Filsafat, pada esensinya, adalah pencarian akan kebijaksanaan, sebuah kompas etis dan logis di tengah lautan informasi. Ia mengajarkan kita berpikir kritis, mempertanyakan segala asumsi, memahami etika rumit di balik AI, dan mencari makna di balik kebahagiaan semu di media sosial. Ini adalah keterampilan hidup yang tak lekang oleh waktu, justru makin krusial di tengah banjir informasi dan tuntutan sosial yang kian absurd.
Lalu, mengapa kemudian ada kesan bahwa filsafat itu tidak relevan, atau parahnya, hanya jadi bahan obrolan omong kosong? mungkin kalian belom melihat fenomena ini!
Jerat Tongkrongan Filsafat
Di sinilah pisau kritik tajam perlu diarahkan pada fenomena “tongkrongan filsafat.” Ini bukan tentang filsafatnya yang salah, tetapi manusianya yang kadang terjebak dalam pusaran aliran-aliran pemikiran sampai lupa daratan. Mereka begitu fasih membahas eksistensialisme ala Sartre sambil mengisap rokok kretek, mendekonstruksi makna “cinta” dengan gaya Derridaian, atau menganalisis “kebahagiaan” ala Epikuros di malam Minggu yang sepi. Mereka mungkin hafal di luar kepala semua argumen tentang Tuhan, keadilan, atau kebebasan, yang sudah diperdebatkan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rusyd ribuan tahun lalu.
Masalahnya, diskusi ini seringkali berakhir di sana, di tongkrongan, di bangku kampus yang dingin, atau di kolom komentar media sosial. Mereka menjadi ajang untuk menunjukkan “kepintaran” bukan kepintaran sejati yang aplikatif, melainkan semacam pamer kamus istilah-istilah sulit yang, jujur saja, kadang mereka sendiri belum benar-benar mengerti esensinya. Mereka bisa berjam-jam membahas “masalah alienasi dalam masyarakat kapitalis,” tetapi lupa bagaimana mengelola uang saku agar tidak overdrawn. Mereka dengan gagah berani mengkritik sistem, tetapi tidak pernah mengambil langkah nyata, sekecil apapun, untuk terlibat atau menawarkan solusi.
Fenomena ini melahirkan kesan bahwa sebagian mahasiswa atau siapa pun yang “keracunan” filsafat tanpa pembumian akhirnya seperti “pengangguran yang sok pintar.” Mereka nyaman membahas konsep-konsep agung yang sudah dikunyah ribuan kali, tanpa pernah bertanya “Bagaimana semua teori ini bisa saya terapkan untuk mengubah realitas di depan mata saya?” Mereka sibuk berrefleksi tentang sistem yang tidak mereka setujui, tetapi lupa berfokus pada diri sendiri. siapa saya, apa yang bisa saya lakukan, dan bagaimana saya bisa menjadi pribadi yang mampu merubah sistem itu, alih-alih cuma meratapi dan berefleksi.
Perlunya Evaluasi
Maka, perdebatan ini bukan tentang menghapus filsafat. Justru, ini adalah sebuah panggilan kolektif. Panggilan bagi para pengajar filsafat untuk merevolusi kurikulum agar tidak hanya mencetak ahli teori, tetapi juga agen perubahan yang berpikir kritis dan bertindak strategis. Panggilan bagi mahasiswa dan seluruh penikmat filsafat untuk melampaui “tongkrongan filsafat” dan menerjemahkan pemahaman mereka menjadi aksi nyata.
Filsafat bukanlah menara gading yang terpisah dari realitas. Ia adalah kompas yang menuntun kita tidak hanya untuk memahami dunia, tetapi juga untuk memiliki keberanian mengubahnya menjadi lebih baik. Relevansi filsafat akan tetap abadi, jika kita mampu menjadikannya pondasi untuk aksi dan inovasi, bukan sekadar bahan obrolan kosong yang disamarkan sebagai kecerdasan bak plato. Inilah saatnya filsafat kembali ke habitat aslinya. Sebagai alat yang memberdayakan manusia untuk menjadi siapa, melakukan apa, dan pada akhirnya, mengubah dunia dengan kebijaksanaan yang nyata, bukan cuma obrolan ngalor-ngidul.

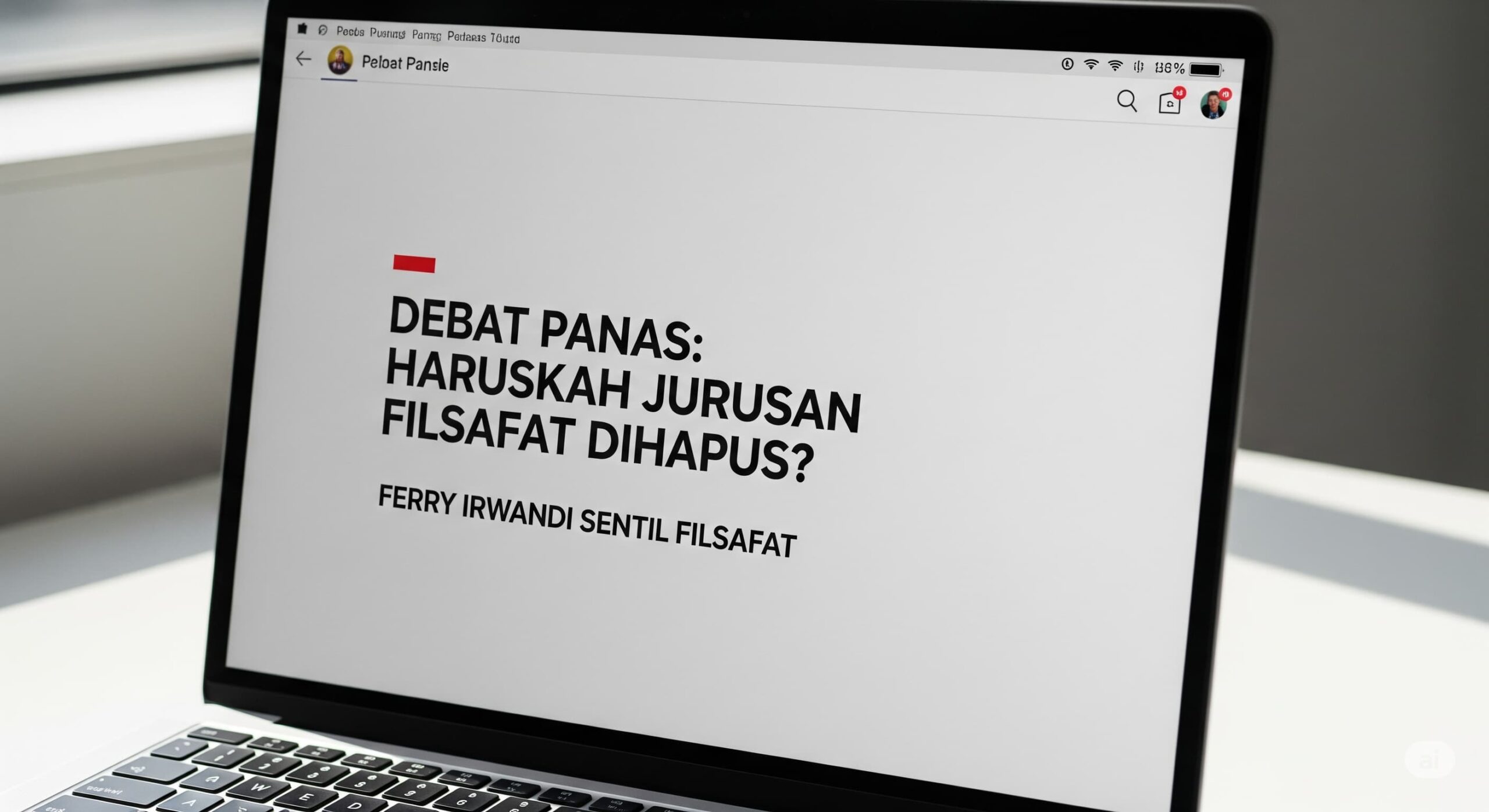

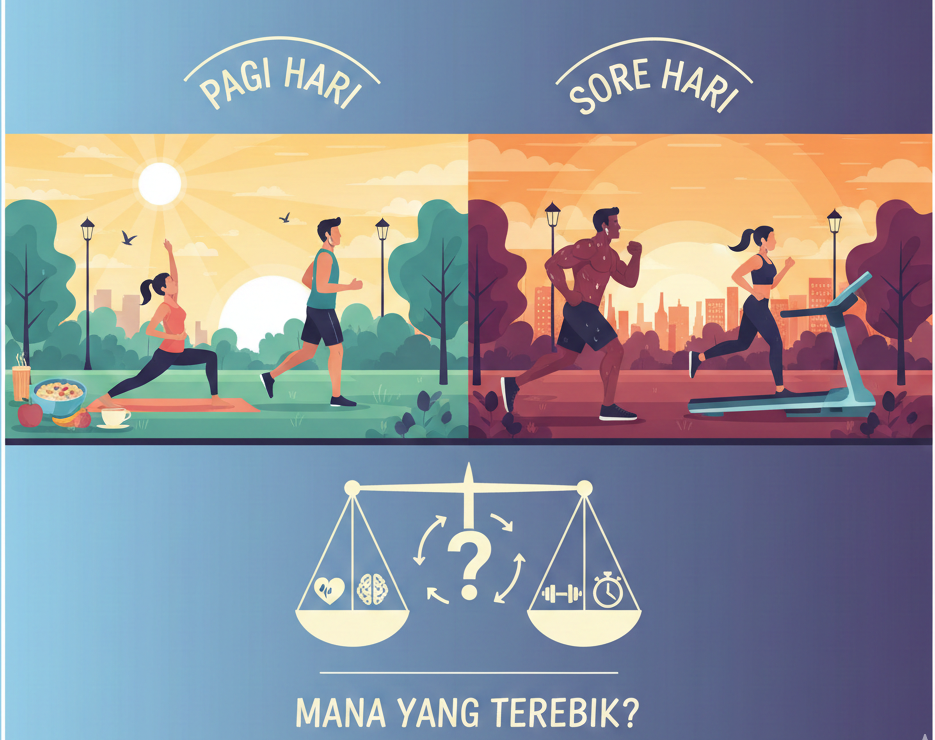

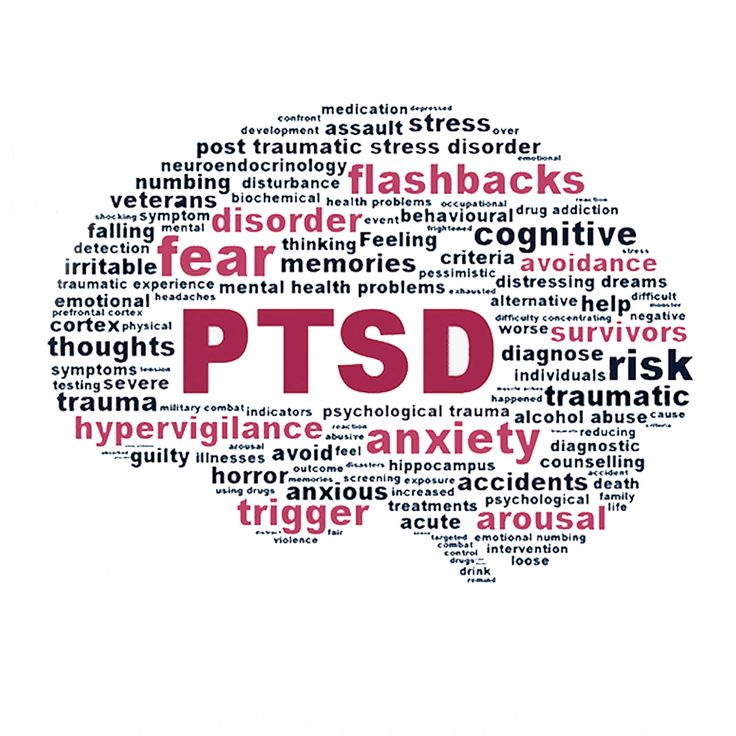

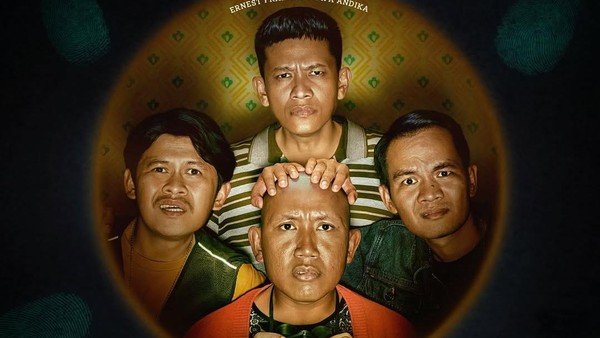
Tinggalkan Balasan