Pernah ngga sih lagi scroll TikTok atau Reels di tengah malam, tiba-tiba lewat sebuah video dengan musik seperti lo-fi melankolis yang bilang: “5 tanda kamu mengidap ADHD yang sering disepelekan?” Awalnya mungkin cuma lewat,
tapi besoknya, konten yang sama bakal muncul lagi, besoknya lagi makin banyak. Tanpa kita sadari pikiran kita mulai menghubungkan dari media sosial ke dunia nyata: “Eh iya juga ya, aku sering lupa naruh kunci motor dan sering susah fokus, jangan-jangan aku beneran ADHD?” Nah, di sinilah jebakan itu dimulai.
Fenomena self-diagnosis atau diagnosis mandiri bukan lagi sekedar untuk mencari tahu, melainkan sekarang ini sudah menjadi tren di kalangan para remaja. Kita saat ini bukan lagi sekedar mencari informasi secara sadar, melainkan kita sedang “disuapi” label kesehatan oleh algoritma yang bahkan ga kenal kita siapa sebenarnya. Kita berada di era dimana perhatian dari sebuah video berdurasi 15 detik terasa lebih nyata dibandingkan obrolan bersama psikolog.
Cara Kerja Algoritma: Mengubah Sedih Menjadi “Sakit”
Menurut pakar data science dan media digital dari Moringa School, algoritma didefinisikan sebagai serangkaian instruksi atau prosedur yang dirancang untuk menganalisis, memproses data, dan menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan otomatis.
Algoritma media sosial dirancang untuk satu tujuan utama: membuat kita bertahan selama mungkin di dalam satu aplikasi. Ketika kamu berhenti sejenak lalu memberikan like, komen, atau menonton konten bertema mental health sampai habis, AI menganggap itu adalah minat utamamu.
- Dampaknya, kamu akan terus-terusan menerima konten sejenis. Saat kamu sedih karena gagal ujian atau putus cinta, algoritma akan terus menyuguhkan konten tentang depresi.
Masalah muncul ketika konten yang lewat adalah penyederhanaan dari gangguan medis yang sangat kompleks. Kesedihan normal manusiawi sering kali diubah menjadi narasi gangguan jiwa demi mendapatkan engagement (interaksi) yang tinggi. Kita terjebak dalam gema informasi yang sempit, yang membuat kita merasa “sakit” hanya karena algoritma bilang begitu.
Romantisasi Label dan Tameng Identitas
Dalam dunia psikologi, diagnosis memerlukan observasi mendalam oleh tenaga profesional, mulai dari wawancara klinis, melihat latar belakang keluarga, hingga tes psikometri yang valid. Psikolog butuh bertahun-tahun belajar untuk bisa memberikan satu diagnosa, sementara kita merasa cukup hanya dengan satu konten di media sosial.
BACA JUGA: Sebuah Tragedi yang Dikirim FYP
Remaja masa kini cenderung mengadopsi label kesehatan mental ini sebagai identitas baru. Ada semacam “romantisasi” terhadap gangguan jiwa. Pernah lihat orang yang dengan bangga menuliskan diagnosa mandirinya di bio media sosial?
Terkadang, label ini justru menghambat pertumbuhan karakter. Seseorang bisa saja berhenti berusaha memperbaiki diri dengan alasan, “Aku nggak bisa berubah, kan aku punya anxiety.” Label tersebut akhirnya bukan lagi petunjuk untuk mencari bantuan, melainkan menjadi tameng atau alasan untuk tidak bertanggung jawab atas tindakan diri sendiri.
Warning Awal, Bukan Kesimpulan Akhir
Kesadaran akan kesehatan mental emang sangat positif, bagus jika kita mengetahui bahwasannya kesehatan jiwa itu sangatlah penting. Kesadaran seharusnya membawa kita ke ruang konsultasi profesional untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
Namun tren saat ini justru membuat remaja berhenti di tahap “mengklaim”. Mengetahui gejala dari internet harusnya menjadi warning awal, bukan kesimpulan akhir. Mengobati diri sendiri melalui informasi yang ada di internet ibaratkan meminum obat tanpa resep dari dokter; mungkin gejalanya sama tapi dosis dan gangguannya bisa sangat berbeda. Jika salah mendiagnosa berarti salah penanganannya, dan itu akan memperburuk kondisi mental yang sebenarnya.
Literasi Digital: Mematikan Layar untuk Kesembuhan
Lalu, apakah kita harus berhenti mengonsumsi konten kesehatan mental? Tentu tidak. Kuncinya adalah literasi digital. Kita harus sadar bahwa konten di media sosial dibuat oleh kreator konten, bukan dokter. Tujuan mereka sering kali adalah viewers dan followers, bukan kesembuhanmu.
Sebagai remaja yang cerdas, kita harus bisa mematikan layar ponsel saat informasi yang masuk mulai terasa menyesatkan atau membuat kita makin cemas. Kita perlu melakukan “detoks informasi” dan mulai memverifikasi apa pun yang kita baca. Jangan biarkan algoritma yang dingin menentukan warna jiwamu yang penuh warna.
Kesehatan jiwa kita terlalu berharga untuk diserahkan kepada algoritma media sosial. Tren boleh datang dan pergi, tetapi dampak dari label diagnosis yang salah akan bertahan seumur hidup.
Jika kamu merasa ada yang benar-benar tidak beres dari tubuhmu, segera letakkan ponsel dan berbicaralah kepada manusia nyata: orang tua yang peduli, sahabat, guru, atau bahkan langsung ke psikolog untuk memastikan keadaanmu. Kesembuhan dan ketenangan jiwa dimulai dari perhatian dan kejujuran para ahli, bukan dari jebakan viral yang mengejar angka.

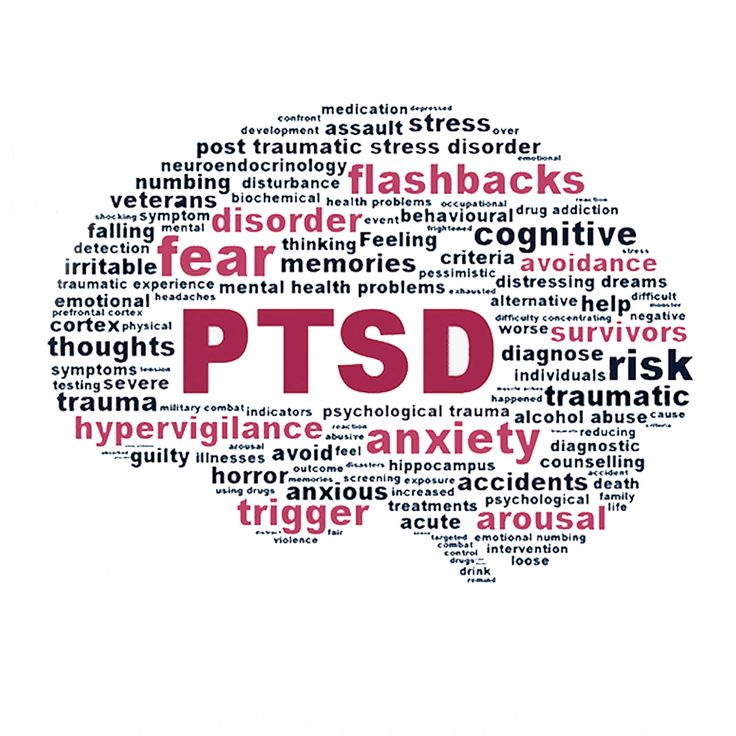





Tinggalkan Balasan