Di balik kesakralan dan keheningan malam 1 Suro, tersimpan sebuah kisah besar tentang politik, budaya, dan visi seorang raja jenius. Ini bukanlah narasi tentang mitos atau hantu, melainkan jejak sejarah tentang bagaimana sebuah kalender menjadi alat pemersatu sebuah kerajaan yang nyaris terbelah.
Sebuah Kerajaan, Dua Waktu
Pada awal abad ke-17, Sultan Agung Hanyokrokusumo (bertakhta 1613-1645 M) memimpin Kesultanan Mataram dengan ambisi besar: menyatukan seluruh tanah Jawa di bawah panjinya. Namun, ia menghadapi masalah fundamental. Rakyatnya hidup dalam dua “zona waktu” budaya yang berbeda.
- Kaum Santri di Pesisir: Masyarakat di pesisir utara Jawa, yang lebih dulu dan intensif berinteraksi dengan pedagang Muslim, menggunakan Kalender Hijriah. Penanggalan berbasis peredaran bulan (qamariyah) ini menjadi acuan utama ibadah dan kehidupan sehari-hari mereka.
- Kaum Abangan di Pedalaman: Mayoritas masyarakat agraris di pedalaman masih setia pada Kalender Saka, warisan kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit. Penanggalan berbasis peredaran matahari (syamsiyah) ini telah menjadi ritme hidup agraris mereka selama berabad-abad.
Perbedaan ini bukan sekadar masalah teknis. Perayaan hari besar, ritual keagamaan, hingga penentuan musim tanam menjadi tidak sinkron. Perpecahan ini adalah penghalang nyata bagi cita-cita persatuan Sultan Agung. Bagaimana mungkin menyatukan sebuah bangsa jika mereka bahkan tidak sepakat tentang hari ini hari apa?
Manuver Jenius pada Tahun 1633
Menghadapi dilema ini, Sultan Agung tidak memaksakan satu sistem dan menghapus yang lain. Sebaliknya, pada 8 Juli 1633 M, ia melahirkan sebuah manuver politik dan budaya yang cerdas: Kalender Jawa.
Ini adalah sebuah karya akulturasi brilian, sebuah kompromi yang dirancang untuk merangkul semua pihak:
- Untuk Kaum Santri: Sultan Agung mengadopsi dasar perhitungan bulan (lunar) dari Kalender Hijriah. Nama-nama hari diadaptasi dari bahasa Arab (Ahad, Senen, dst.), dan nama-nama bulan pun di-Jawa-kan dari nama bulan Hijriah. Bulan Muharram menjadi Suro, Safar menjadi Sapar, dan seterusnya. Nama “Suro” sendiri diambil dari “Asyura” (hari ke-10 Muharram), sebuah hari yang sangat dimuliakan dalam Islam, untuk memberi bobot kesucian pada bulan pertama ini.
- Untuk Kaum Abangan: Dalam sebuah langkah krusial, Sultan Agung tidak mengulang tahun menjadi tahun 1. Ia justru melanjutkan angka tahun dari Kalender Saka yang sudah berjalan. Maka, setelah tahun 1554 Saka, tahun berikutnya adalah 1555 Jawa. Keputusan ini secara simbolis menyatakan bahwa peradaban Jawa tidak terhapus, melainkan memasuki babak baru yang selaras dengan nilai-nilai Islam.
Dengan cara ini, Sultan Agung berhasil menyatukan rakyatnya secara psikologis. Kaum santri merasa diakomodasi karena sistemnya Islami, sementara kaum abangan merasa dihargai karena kesinambungan sejarah mereka tidak diputus.
Warisan yang Hidup: Dari Politik Menjadi Spiritualitas
Penciptaan Kalender Jawa lebih dari sekadar reformasi penanggalan; ia adalah fondasi pembangunan bangsa. Kebijakan ini terbukti berhasil:
- Mempersatukan Rakyat: Dengan satu kalender, seluruh rakyat Mataram kini hidup dalam ritme waktu yang sama, yang berpusat pada otoritas keraton.
- Memfasilitasi Islamisasi: Proses Islamisasi berjalan lebih halus dan efektif karena disajikan dalam “wadah” budaya yang sudah akrab bagi masyarakat Jawa.
- Mengukuhkan Otoritas Raja: Sultan Agung memantapkan posisinya sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin agama dan budaya (Panatagama).
Seiring berjalannya waktu, makna 1 Suro berevolusi. Dari yang semula merupakan momentum politik, ia berubah menjadi momen spiritual yang mendalam. Spirit pergantian tahun baru ini kemudian diisi dengan filosofi Jawa luhur, yaitu eling lan waspada sebuah ajakan untuk selalu “ingat” pada Sang Pencipta dan “waspada” terhadap godaan hawa nafsu.
Dari filosofi inilah lahir berbagai tradisi yang kita kenal hari ini, seperti tirakatan (berjaga semalaman untuk berdoa), jamasan pusaka (menyucikan benda pusaka sebagai simbol penyucian diri), dan topo bisu mubeng beteng (berjalan dalam keheningan mengelilingi benteng keraton sebagai bentuk introspeksi). Semua ritual ini adalah gema dari semangat persatuan dan penyucian diri yang dicanangkan oleh Sultan Agung hampir empat abad yang lalu.
BACA JUGA: Pesanggrahan Ambarketawang: Episode Awal Kraton Jogja dari Gunung Gamping
Maka, ketika kita hari ini menyaksikan keheningan malam 1 Suro, kita tidak hanya melihat sebuah tradisi. Kita sedang menatap warisan dari sebuah keputusan sejarah yang luar biasa sebuah bukti abadi bagaimana budaya dapat menjadi alat pemersatu yang jauh lebih kuat dari apa pun.



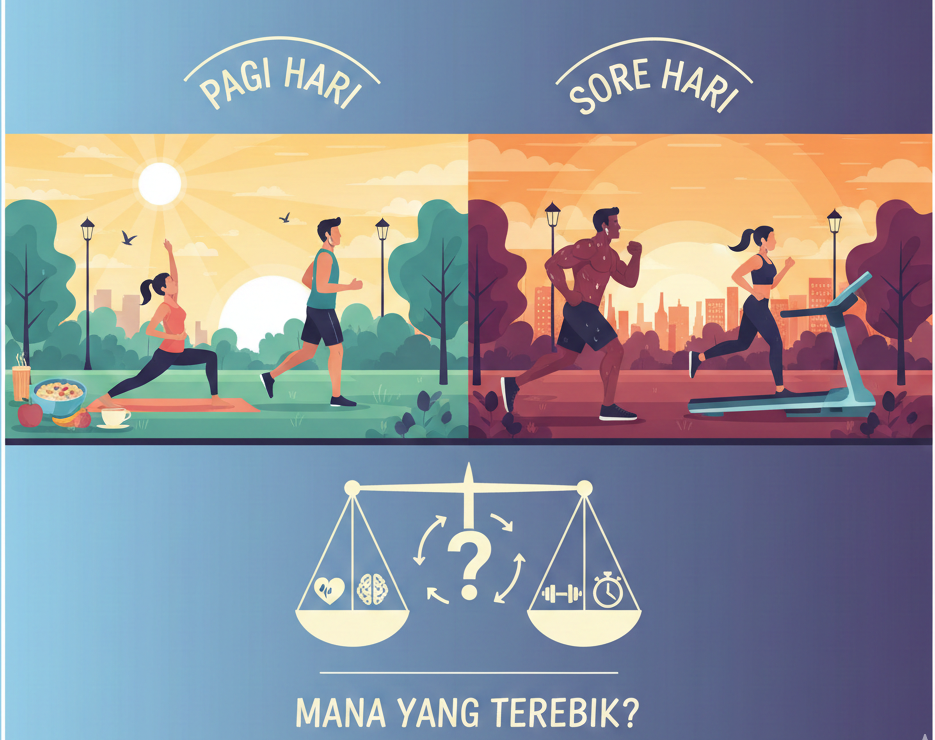

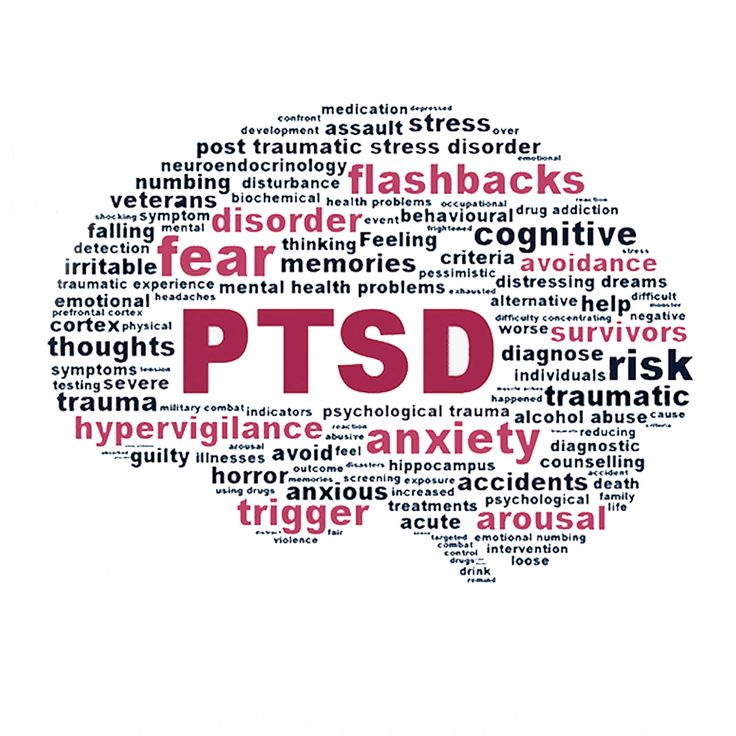

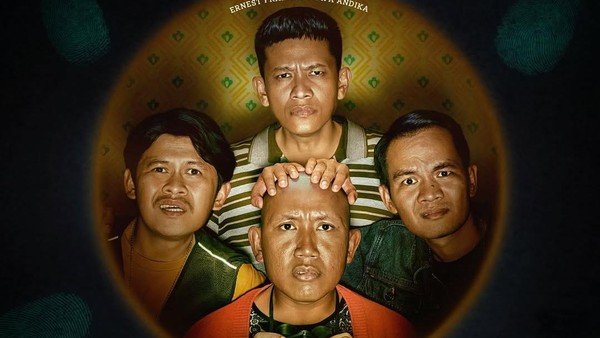
Tinggalkan Balasan