Pramoedya Ananta Toer, atau Pram, dalam lembaran sejarah dikenal sebagai penulis otodidak yang menaruh perhatian besar terhadap penelitian sejarah. Perkembangan historiografi, yang tidak dapat dilepaskan dari konteks zamannya, turut memengaruhi pemikiran Pram. Sebagai contoh, Seminar Sejarah Nasional 1957 di Yogyakarta menghasilkan konsep sejarah Indonesia-sentris, di mana sejarah dipandang sebagai bagian dari politik untuk menyatukan dan memperkuat rasa nasionalisme. Akibatnya, sejarah kerap diidentikkan sebagai bagian dari kekuasaan. Hal ini terlihat pada narasi Soekarno dan Mohammad Yamin yang mengglorifikasi masa silam di bawah kekuasaan Majapahit, Sriwijaya, serta kebesaran Patih Gadjah Mada.
Persepsi lain yang muncul adalah mengenai kebangkitan nasional yang dianggap bermula sejak era Boedi Oetomo (1908) sebagai embrio nasionalisme. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah, namun Pram memiliki pendapat berbeda; baginya, era Kartini adalah awal mula kebangkitan nasional Indonesia.
Rupanya, Pram ingin mengawali sejarah kebangkitan bangsa melalui perspektif sejarah perempuan. Keberadaan perempuan di Jawa dan wilayah Indonesia lainnya pada masa silam kerap terpinggirkan oleh budaya patriarki, khususnya pada era 1950-1960an. Melalui novel Panggil Aku Kartini Sadja yang terbit pada 1962, Pram membuat gebrakan dalam kurungan sejarah umum yang biasanya menempatkan laki-laki, politik, dan orang-orang besar sebagai pusat narasi. Dalam novel tersebut, Pram menyampaikan perjuangan kesetaraan dan kemerdekaan perempuan melalui tulisan.
Setahun sebelumnya, Pram juga menulis sejarah orang Tionghoa berjudul Hoakiau di Indonesia, yang mengulas kontribusi etnis Tionghoa mulai dari budaya hingga teknologi. Sekali lagi, Pram hadir dengan alternatif historiografi yang tidak terpaku pada kekuasaan, melainkan menjadi pionir utama bagi sejarah kerakyatan. Mengutip pendapat Hilmar Farid (2013), penyusunan sejarah menurut Pram harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sosialisme, Pancasila sebagai dasar negara, serta program umum Manipol.
Pram tidak hanya menjadi perintis sejarah sosial, tetapi juga mengawali ciri penulisan sejarah yang berorientasi pada aspek kerakyatan, senada dengan gagasan Mohamad Ali dalam Seminar Sejarah Nasional 1957. Namun, memori kolektif kita lebih mengenal Sartono Kartodirdjo melalui disertasinya, Pemberontakan Petani Banten 1888 (1966). Hal ini wajar karena Sartono adalah sejarawan akademik yang terlatih dan “didesain” oleh universitas melalui riset ilmiahnya di Amsterdam. Sementara itu, Pram hanyalah sejarawan otodidak yang mengampu perkuliahan sejarah di Universitas Res Publica (kini Universitas Trisakti) pada tahun 1960-an. Pram menyadari bahwa ia bukanlah sosok yang terampil dalam metode penulisan sejarah yang kritis dan akademis. Meski Pram bukan sejarawan akademis sebesar Sartono, kita harus mengakui bahwa melalui karya-karyanya, ia menjadi pelopor utama dalam penulisan sejarah rakyat kecil (history from below) dan berupaya menuju sejarah nasion.
Selain mempelopori sejarah sosial, Pram juga mengajarkan verifikasi dan penggunaan sumber mulai dari surat kabar hingga wawancara kepada mahasiswanya. Ia mengumpulkan bahan-bahan yang kemudian disusun sebagai penguat argumentasi dalam Tetralogi Buru dan novel-novel lainnya. Pram mengajarkan bahwa arsip bukan hanya dokumen yang dipublikasikan negara; arsip non-institusional pun tidak boleh dikesampingkan. Dalam diktat Sedjarah Modern Indonesia (1964), Pram menggunakan sumber surat kabar sebagai bahan ajar. Buku tersebut unik karena tidak dimulai dari masa pra-aksara, melainkan dari masa kolonialisme. Dapat dikatakan, Sedjarah Modern Indonesia menjadi kompas pembelajaran sejarah kala itu, di mana Pram berperan menyumbangkan historiografi Indonesia-sentris pada tahun 1960-an.
Pram mengkritik keras historiografi kolonial-sentris yang memusnahkan arsip, menyingkirkan karya orang lain, dan menjauhkan tokoh penting dari pendukungnya. Kritik ini tervisualisasi dalam novel Rumah Kaca, di mana Jacques Pangemanann (polisi Hindia Belanda) mengontrol pergerakan Tirto Adhisoerjo (Minke). Pangemanann memberangus gerakan kaum bumiputera melalui pemusnahan arsip dan pembuangan orang. Ironisnya, hal serupa dialami Pram pasca-Peristiwa 30 September. Diktat, karya, surat kabar, hingga arsip penelitiannya dimusnahkan. Pemusnahan ini adalah upaya penghilangan jejak intelektual Pram sebagai penulis sekaligus oposisi penting penandatangan Manifes Kebudayaan. Selain menghancurkan kiprah fisik, negara dan agen kebudayaannya juga melakukan framing melalui media dan simbol kebudayaan sebagai bentuk hegemoni.
Menurut Antonio Gramsci, ketertundukan suatu kaum dapat diperoleh melalui ideologi kelas yang menghegemoni negara. Hegemoni Orde Baru tidak hanya menyasar tokoh-tokoh yang dicap “Kiri”, melainkan juga memolitisasi historiografi. Negara membutuhkan sejarawan untuk menulis sejarah sebagai tindak lanjut Seminar 1957. Sayangnya, politik historiografi ini tidak merangkum konsep “Indonesia-sentris” secara utuh, apalagi setelah mundurnya Sartono Kartodirdjo dari tim penulis Sejarah Nasional Indonesia (SNI). Akhirnya, SNI yang dihasilkan (terdiri dari 6 jilid) justru tidak jauh berbeda dari narasi kolonial-sentris, penuh pemutarbalikkan fakta, serta narasi yang mengada-ada dan cenderung Jawa-sentris.
Narasi tentang “dijajah tiga setengah abad” termanifestasi dalam pelajaran sejarah sekolah, dengan ilustrasi hitam-putih: Belanda sebagai penjahat dan bumiputera sebagai pahlawan. Mengutip studi Bambang Purwanto (2006), narasi ini adalah pembodohan karena menyamakan negara kolonial dengan sejarah kolonialisme Belanda. Purwanto menegaskan bahwa VOC dan Hindia Belanda adalah dua variabel berbeda. VOC memandang kolonialisme sebagai aktivitas ekonomi-politik, sedangkan Hindia Belanda adalah konsep negara kolonial yang memiliki unsur pemerintahan, pertahanan, dan integrasi wilayah. Ada kerancuan dalam memahami sejarah: tidak seluruh wilayah barat Indonesia dikuasai VOC, sementara bagian timur dan tengah justru berada dalam bayang-bayang Portugis. Hindia Belanda baru benar-benar berdiri sebagai negara (seperti konsep wilayah Indonesia saat ini) pada abad ke-20, setelah Aceh takluk.
Bias sejarah serupa terjadi dalam buku sekolah mengenai Herman Willem Daendels, yang digambarkan sebagai pembunuh kejam dalam proyek Jalan Raya Pos. Pram, melalui Jalan Raya Pos, Jalan Daendels (selesai ditulis 1995, terbit 2005), mematahkan mitos yang telah terinternalisasi dalam ingatan pelajar tersebut. Pram mengungkap fakta bahwa dalam pembuatan jalan di Jawa Barat (Bogor, Bandung, hingga Sumedang) yang berbukit-bukit, penggunaan dinamit memang berkontribusi pada kematian pekerja. Namun, di sisi lain, keterlibatan penguasa bumiputera atau “londo ireng” yang menjadi mandor turut memperparah keadaan dengan mengorupsi hak-hak para pekerja.
Pram menyoroti bahwa praktik korupsi sudah terjadi sejak era Daendels, menyebabkan banyaknya korban jatuh akibat minimnya kontrol pemerintah dan kejahatan sesama bumiputera. Maka, tidak heran bila Daendels disudutkan sebagai pelaku genosida pertama abad ke-19. Pram juga mengomparasikan peristiwa ini dengan genosida di Banda oleh J.P. Coen, kejahatan Cultuurstelsel oleh van den Bosch, dan aksi Kapten Westerling di Sulawesi. Dalam bahasannya, Pram mengaitkan penderitaan masa lalu itu dengan perbudakan yang dialaminya sendiri bersama tahanan politik di Pulau Buru. Mereka dipaksa bekerja membangun kamp dan pertanian, membuka hutan yang tak jarang menimbulkan korban jiwa.
BACA JUGA: Thilly Weissenborn Pelopor Fotografer Perempuan Hindia Belanda
Dalam kasus ini, Pram tidak hanya bertindak sebagai penulis sejarah, tetapi juga pelaku dan pencipta sumber sejarah atas peristiwa di Pulau Buru. Perbudakan selama kurang lebih 15 tahun itu dinarasikan Pram dalam bagian Jalan Raya Pos, Jalan Daendels. Pram juga mendekonstruksi mitos jalan “seribu kilometer”. Ia mencatat bahwa para pekerja sebenarnya hanya membuat jalan utama dari Batavia ke Buitenzorg, lalu disambung ke Bandung hingga Cirebon. Jalan di pesisir utara Jawa sesungguhnya telah ada sejak masa pra-kolonial. Pram menyadari banyak informasi simpang siur dalam sejarah resmi (SNI) yang luput menyoroti rakyat kecil.
Keberpihakan Pram pada rakyat kecil telah tumbuh sejak ia berkecimpung di Lekra. Perkenalannya dengan Rivai Apin, A.S. Dharta, dan tokoh Kiri lainnya mengarahkan pemikirannya pada politik kerakyatan. Bahkan, seandainya Pram masih hidup saat ini dan menyaksikan era yang polanya hampir mendekati Orde Baru, ia niscaya akan tetap bersuara dengan ciri khasnya. Seperti pada tahun 1999, saat memberi kuliah umum di Perpustakaan Nasional RI, Pram berkomentar pedas mengenai Indonesia sebagai negara maritim yang justru dikuasai Angkatan Darat. Menurutnya, bangsa ini tidak belajar dari sejarah kekalahan Hindia Belanda oleh Jepang yang diawali penetrasi laut sebelum penguasaan darat. Sikap kritisnya juga terlihat saat Gus Dur, Presiden ke-4 RI, meminta maaf kepada korban politik 1965; bagi Pram, itu hanyalah basa-basi karena negara tidak serius memperhatikan nasib para korban.

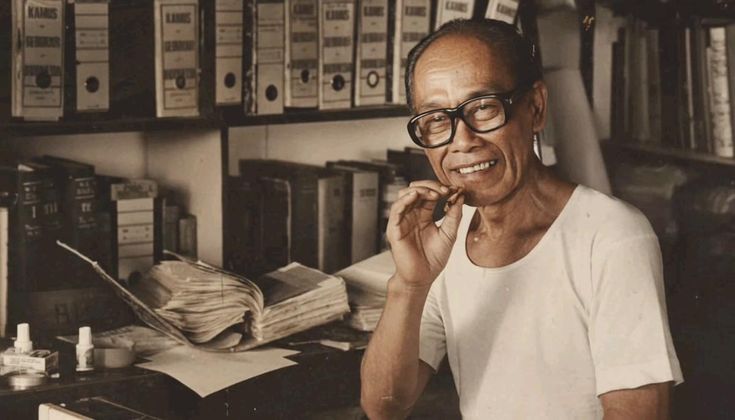



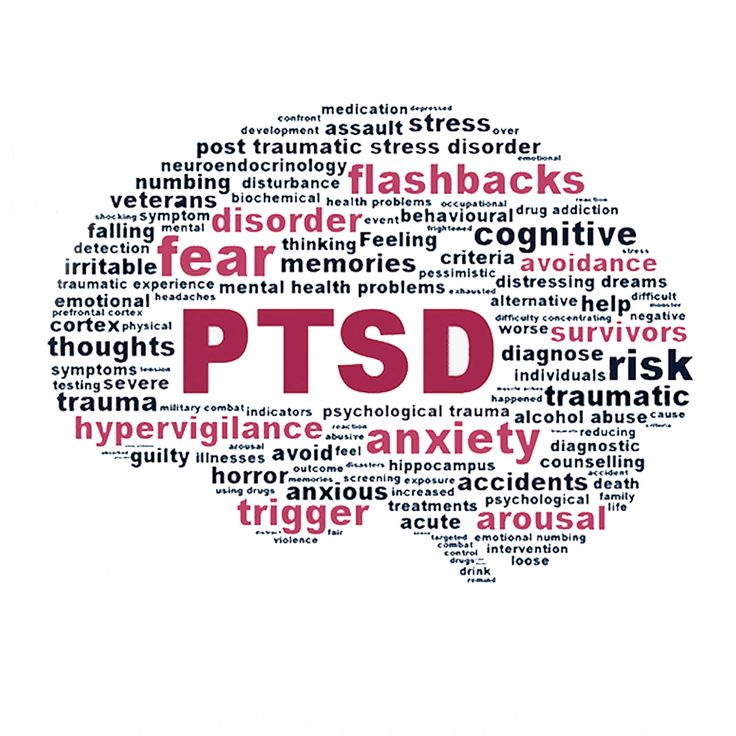


Tinggalkan Balasan