Film horor Indonesia belakangan ini mengalami perkembangan pesat. Beberapa film terasa segar dan berani bereksperimen, tapi sisanya? Nol besar. Masih pakai formula yang sama dan hanya didaur ulang. Pernah nggak sih nonton film horor terus mikir, “Lho, suasananya kok mirip lagi?”
Nah, itu karena banyak film sukses kita masih mengandalkan kisah mistis dari tradisi dan budaya lokal, terutama yang sudah akrab di telinga penonton. Menariknya, dari sekian banyak budaya di Indonesia, film horor kita hampir selalu bersumber dari tradisi Jawa. Seolah-olah, rasa takut cuma bisa hidup lewat ritual, kepercayaan, dan adat Jawa.
Tapi kenapa produser terus-menerus mengulang formula ini? Apakah ini murni soal permintaan pasar, atau ada faktor struktural yang lebih kompleks?
Dominasi Angka dan Monopoli Naratif
Pertama, ada angka yang tidak bisa dibantah. KKN di Desa Penari (2022) meraup 9,2 juta penonton dengan estimasi bujet Rp 5-8 miliar. Sewu Dino (2023) menyusul dengan 4,8 juta penonton, dan Danur (2017) mencatat 3,7 juta penonton hingga melahirkan franchise lima film.
Sementara itu, film horor yang mencoba keluar dari zona aman Jawa menunjukkan performa yang jauh berbeda. Kuyang: Sekutu Iblis yang Selalu Mengintai (2024), meski mengangkat mitos Kalimantan dengan serius, hanya mencapai sekitar 600-800 ribu penonton. Pernik Khilaf (2024) yang berlatar Aceh bahkan lebih sedikit lagi.
Rasa frustrasi ini disuarakan oleh Timothy Fidialo, kritikus film dan host kanal YouTube Ngelalantur. Ia mengkritik keras kemalasan industri yang lebih memilih mengadaptasi utas viral Twitter (seperti kisah-kisah ala SimpleMan) demi built-in audience, ketimbang menggali kekayaan folklor asli Indonesia yang beragam. Menurut Timothy, sekitar 70% horor lokal didominasi tema pesugihan Jawa, menciptakan monopoli naratif.
Keresahan ini diamini netizen. Banyak yang menyayangkan betapa kayanya budaya Indonesia yang belum terjamah, sementara yang lain mulai jenuh karena budaya Jawa terus-menerus diasosiasikan dengan hal mistis. Kesimpulannya satu, industri butuh revolusi.
Jebakan “Comps” dan Geografi Penonton
Dalam industri film Indonesia, keputusan kreatif tidak pernah berdiri sendiri. Setiap pitch project harus melewati tahap “comps” atau comparable titles yang jadi acuan investor. Jika seorang produser mengajukan film horor berlatar Papua atau Sulawesi, pertanyaan pertama yang muncul adalah: “Film sejenis terakhir yang sukses apa?” Ketika jawabannya kosong, pitch mati di tempat.
Fenomena ini diperparah oleh struktur permodalan film Indonesia yang sangat bergantung pada pre-sales ke distributor dan eksibitor (jaringan bioskop). Mereka akan menilai potensi film berdasarkan track record tema serupa. Film dengan setting Jawa memiliki “proven market” alias data historis yang solid. Film dengan tema lain? Spekulasi.
Belum lagi soal geografi penonton. Data mencatat bahwa jumlah bioskop di Pulau Jawa menempati posisi tertinggi dengan 345 bioskop. Wilayah di Pulau Jawa menyumbang hampir setengah dari total penjualan tiket nasional. Artinya, film yang tidak “berbicara” dalam bahasa kultural Jawa secara otomatis kehilangan akses ke mayoritas pasar.
BACA JUGA: Film Horor Indonesia: Klise atau Magis?
Pertanyaan paling mendasar adalah, kenapa formula ini diulang terus sejak era 2000-an sampai sekarang? Jawabannya bukan sesederhana “produser malas” atau “kurang kreatif”, melainkan ada mekanisme struktural yang membuat mereka terperangkap.
Berikut adalah bedah masalahnya:
1. Warisan Kesuksesan yang Jadi Kutukan
Jejak formula horor Javasentris ini sebenarnya bisa ditarik mundur ke era Suzanna di tahun 1980-an, tapi titik balik modernnya ada di Jelangkung (2001). Film ini meraup 1,8 juta penonton dan menciptakan template “anak muda main permainan mistis Jawa dilanjutkan teror supernatural”.
Setelah Jelangkung, hampir setiap produser horor mencoba meniru kesuksesannya. Lahirlah Tusuk Jelangkung (2003), franchise Tali Pocong Perawan (2008-2012), hingga puncaknya adaptasi utas viral macam Sewu Dino yang berhasil meraup 4 juta lebih penonton. Setiap kesuksesan memperkuat kepercayaan bahwa “ini yang dicari pasar”. Upaya keluar dari formula ini memang ada, tapi nasibnya hampir selalu jadi footnote dalam sejarah box office Indonesia.
2. Permintaan Pasar atau Ciptaan Pasar?
Ini pertanyaan ayam-dan-telur yang paling rumit. Apakah penonton Indonesia memang “mau” horor Jawa, atau mereka sebenarnya tidak punya pilihan lain? Jawabannya: keduanya.
Masalahnya, penonton tidak pernah diberi kesempatan memilih secara adil. Bayangkan ketimpangannya:
- Horor Jawa: Bujet besar (8-15 M), marketing masif 3-4 bulan, ratusan layar, dan slot prime time.
- Horor Non-Jawa: Bujet minim (3-5 M), marketing seadanya, layar terbatas, dan dukungan distributor minimal.
Ketika film non-Jawa tidak mencapai target, kesimpulannya sering kali meleset: “Tuh kan, penonton memang tidak mau tema di luar Jawa.” Padahal, pertarungannya tidak fair sejak awal.
BACA JUGA: The Silence of the Lambs dan Kemunduran Horor Indonesia
Lebih menarik lagi, ada fenomena self-fulfilling prophecy. Karena penonton terbiasa dengan horor Jawa, ekspektasi mereka terbentuk ke arah sana. Ketika ada film horor baru, mereka (tanpa sadar) mencari elemen familiar: gamelan, pocong, ritual mistis. Film yang tidak punya elemen itu sering dinilai “kurang horor” atau “tidak seram” bukan karena jelek, tapi karena tidak sesuai template di benak mereka.
3. Ketika Produser Berani, Tapi Pasar Belum Siap
Bukan berarti tidak ada produser yang mencoba. Ada, dan cukup banyak. Tapi hasilnya sering kali mengecewakan dari perspektif angka.
- Pengabdi Setan (2017): Joko Anwar mencoba membuat horor yang lebih universal. Setting-nya tidak spesifik Jawa (meski lokasi di Jawa), dan horornya lebih atmosferik daripada ritual-driven. Hasilnya sukses besar (4 juta+ penonton), membuktikan penonton bisa menerima horor yang tidak terlalu Javasentris asal eksekusinya bagus.
- Saranjana: Kota Ghaib (2023): Contoh berani yang keluar dari zona nyaman. Berdasarkan urban legend Kalimantan Selatan, film ini meraup 1,2 juta penonton. Angka yang solid, tapi tetap jauh dari blockbuster horor Jawa.
- Kuyang & Suanggi (2024): Dua upaya diversifikasi terbaru. Respons komunitas lokal sangat positif; orang Kalimantan dan Papua bangga mitos mereka diangkat. Tapi, kebanggaan itu tidak otomatis berubah jadi tiket bioskop karena distribusi terbatas dan awareness rendah.
4. Investor
Ini bagian paling krusial. Investor memiliki power sangat besar, bukan hanya memberi modal, tapi menentukan arah kreatif. Sering kali investor meminta “elemen Jawa” sebagai syarat pendanaan demi Return on Investment (ROI) yang lebih reliable.
Siklus setannya begini: Produser pitch tema non-Jawa → Investor minta “safety net” elemen Jawa → Produser kompromi → Film jadi setengah-setengah → Hasil biasa saja → Investor makin yakin tema non-Jawa tidak laku.
Investor besar seperti MD Pictures, Screenplay, atau Rapi Films juga menjaga brand protection. Mereka sudah punya reputasi dengan horor Jawa, sehingga eksperimen dianggap berisiko mendilusi brand equity mereka.
5. Sistem Pre-Sales yang Memaksa Konformitas
Mayoritas film dibiayai lewat pre-sales (menjual hak distribusi sebelum produksi). Distributor hanya mau beli film yang diyakini laku berdasarkan data masa lalu.
Jika produser menawarkan horor Papua, distributor mungkin menawar harga rendah (misal: 40% dari harga film horor Jawa) dengan alasan risiko tinggi. Akibatnya: bujet rendah, kualitas kompromi, film tidak perform, dan siklus berulang lagi.
6. Tidak Ada Safety Net untuk Eksperimen
Di negara maju seperti Korea (KOFIC) atau Perancis (CNC), ada lembaga pemerintah yang mendanai film eksperimental yang “berisiko secara komersial tapi penting secara kultural”.
Di Indonesia, meski ada BPI atau Kemenparekraf, aksesnya terbatas dan birokratis. Produser yang mau eksperimen harus pakai dana swasta alias siap rugi sendiri. Ini membuat eksperimen jadi privilege produser berkantong tebal.
Lantas, bagaimana dengan produser pemula? Sayangnya, tidak ada pilihan lain selain ikut formula yang sudah terbukti, Jawa adalah kunci.





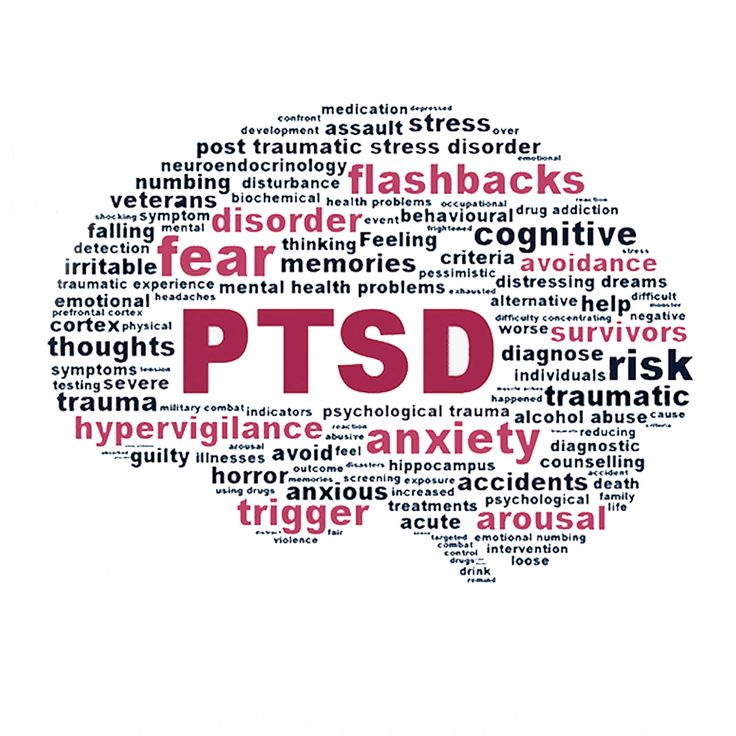


Tinggalkan Balasan