Jauh sebelum arena Hunger Games ada, ada sebuah novel tergelap dari Stephen King (ditulis sebagai Richard Bachman) “The Long Walk”. Selama beberapa dekade, materi yang dikenal brutal dan nihilistis ini dianggap “tidak bisa difilmkan”. Kini, naskah terkutuk itu jatuh ke tangan Francis Lawrence. Sutradara yang terbiasa memvisualisasikan arena distopia itu kini ditantang untuk mengangkat premis yang jauh lebih sederhana, namun tak terhingga lebih kejam.
Latar belakangnya adalah cerminan dari masyarakat kita yang rusak, di bawah tatapan dingin sebuah rezim totaliter, di tengah krisis ekonomi yang meremukkan, puluhan anak laki-laki remaja secara sukarela mendaftar untuk sebuah tontonan nasional.
Hanya ada suara langkah kaki yang seragam. Puluhan siluet muda itu merobek kabut pagi di sebuah lanskap terpencil yang bisu, bergerak dalam irama yang monoton. Ini adalah “The Long Walk”. Sebuah prosesi tanpa henti di mana peraturannya adalah kesederhanaan yang absolut, teruslah berjalan. Jika kau melambat, kau mati. Ini bukanlah sebuah perlombaan. Ini adalah metafora sempurna dari sebuah sistem.
Perjalanan itu sendiri adalah mesin konformitas yang absolut, entah kau menyebutnya totaliterisme atau kapitalisme predatoris. Ia adalah cerminan dari tuntutan masyarakat yang tak kenal lelah, “Terus bergerak maju. Ikuti aturan. Jangan berhenti.” Sistem tidak peduli pada penderitaanmu, mimpimu, atau cintamu. Ia hanya menuntut kepatuhanmu. Kematian adalah hukuman yang efisien bagi mereka yang gagal beradaptasi, atau bagi mereka yang sekadar berani beristirahat. Ini adalah eksistensialisme modern yang dipreteli hingga ke tulangnya, kita berjalan dari lahir sampai mati, namun tujuannya adalah ilusi. Yang nyata hanyalah “Perjalanan” itu sendiri.
Lalu mengapa mereka berjalan? Mereka berjalan karena “Hadiah”. Sebuah janji palsu untuk mendapatkan “apa pun yang kau inginkan.”
Hadiah ini adalah kebohongan terbesar yang membuat roda sistem terus berputar. Ia adalah “American Dream“ yang telah membusuk, ditawarkan kepada mereka yang terdesak oleh keputusasaan. Sistem ini berbisik, “Kalahkan semua orang, jadilah yang terakhir berdiri, dan kau akan mendapatkan segalanya.” Namun, pesan tersiratnya jauh lebih brutal. Hadiah itu tidak ada artinya. Bagaimana mungkin materi bisa membayar lunas trauma menyaksikan puluhan kawanmu mati di sampingmu? Pemenangnya tidak memenangkan apa-apa selain kehampaan.
Di menara gadingnya, Sang Mayor mengawasi. Ia adalah simbol dari kekuasaan otoriter yang dingin, birokratis, dan tak berperasaan. Ia bukan tiran yang histeris, ia adalah manajer yang efisien dari sebuah mesin pembunuh. Tapi ia bukan penjahat utamanya.
BACA jUGA: Bedah Film “The Cabin In The Woods”: Refleksi Otoritarianisme dan Paradoks Kemanusiaan
Kekejaman ini bisa ada karena ada permintaan. Penonton kita adalah kaki tangannya. Penderitaan anak-anak muda ini telah menjadi komoditas, sebuah tontonan massal bagi masyarakat yang telah mati rasa. Kita telah belajar mengonsumsi tragedi sebagai hiburan, dan dengan demikian, kita turut menopang sistem yang menciptakannya.
Dan sistem ini memilih korbannya dengan cermat, anak-anak muda. Ini adalah kekejaman tertingginya. Masa depan, harapan, dan potensi direduksi menjadi bahan bakar sekali pakai. Sistem ini tidak hanya menindas, ia mengkanibalisasi generasinya sendiri untuk terus hidup.
Di neraka inilah kemanusiaan diuji. Di jalan yang kejam ini, dua kutub filosofis berbenturan dalam diri Ray Garraty dan Peter McVries. Garraty adalah harapan yang rapuh, ia percaya pada ikatan persahabatan, ia menolak kehilangan kemanusiaannya. McVries adalah sinisme yang sudah “mati” bahkan sebelum ia mulai, ia melihat “Hadiah” sebagai lelucon getir. Ironisnya, persahabatan justru bersemi di ladang pembantaian ini. Naluri untuk saling membantu bersinar paling terang, tepat ketika naluri untuk bertahan hidup menuntut mereka saling menghancurkan.
Pada akhirnya, garis finis bukanlah pembebasan. Itu adalah paradoks terakhir.
Kemenangan adalah kekalahan terbesar. Pemenang tidak dibebaskan. Ia selamat secara fisik, tetapi jiwanya telah dieksekusi di sepanjang jalan. Hadiahnya adalah trauma abadi, ia akan selamanya dihantui oleh wajah-wajah mereka yang tumbang. Ia kini menjadi monumen hidup, bukti paling nyata dari keberhasilan sistem.
“The Long Walk” bukanlah cerita tentang siapa yang menang. Ini adalah narasi tentang proses di mana jiwa dilucuti, lapis demi lapis, hingga yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang terus berjalan, simbol sempurna dari kepatuhan absolut. Perjalanan itu tidak pernah benar-benar berakhir bagi orang yang selamat.





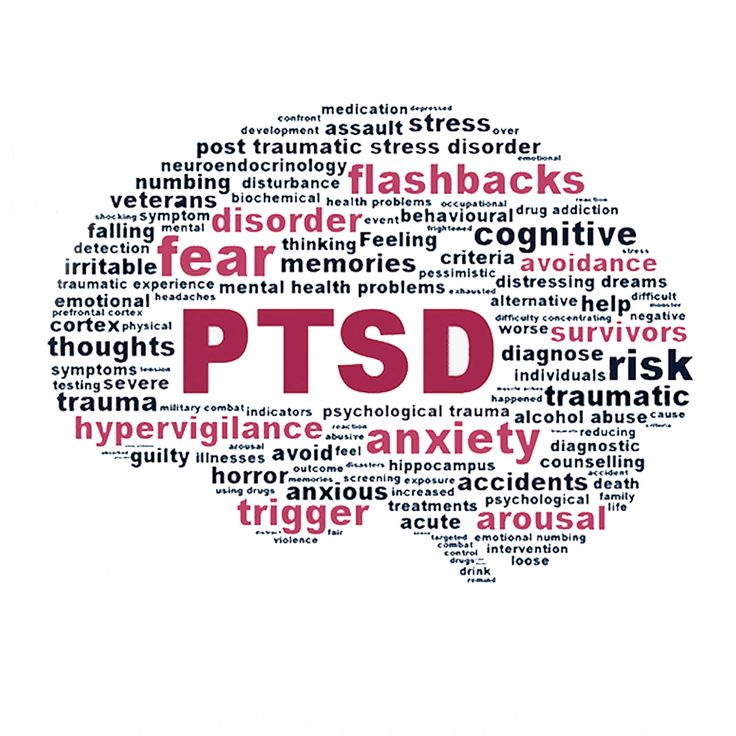


Tinggalkan Balasan